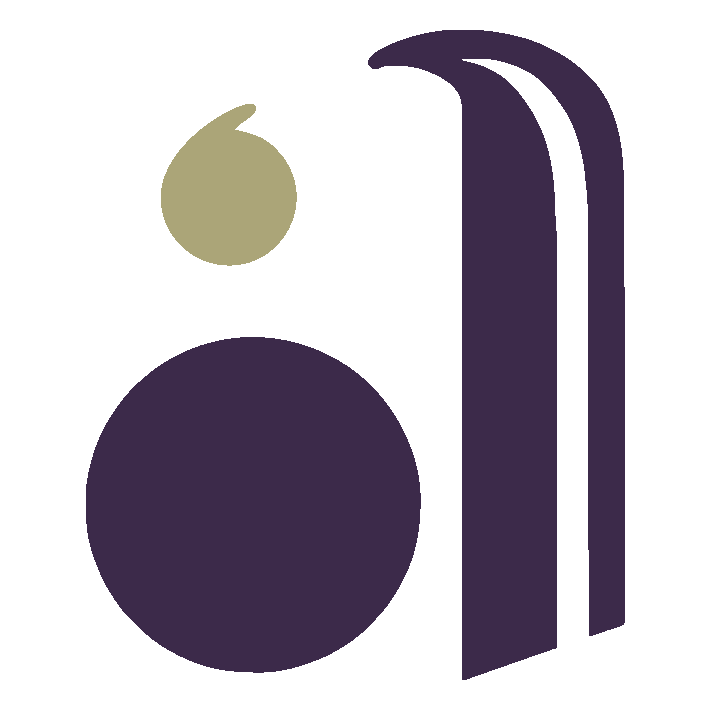Al-Qur'an
Al-Qur'an: Bekerja sebagai Jalan Spiritualitas
Islah Gusmian
Kamis, 28 Agustus 2025 | 14:17 WIB
Menurut Al-Qur'an, bekerja itu membangun peradaban, tidak sekedar mengenyangkan perut atau agar punya fasilitas pribadi.

Di suatu pagi, di Bunderan Pacet Mojokerto, rasa dingin masih menyergap. Saya berkeliling mengusir deru dingin, menyaksikan para perempuan mulai gumrigah, menjemput rezeki: menjajakan aneka makanan ringan, buah-buahan, jajanan pasar, hingga depot nasi.
Nabi mengajarkan kita menghindari tidur usai salat Subuh. Karena saat itu momentum untuk mengawali bekerja, mendulang rezeki bermula. Para perempuan di Bundaran Pacet pagi itu, menghidupkan pesan Nabi tersebut dalam laku secara kongkret, menghargai hidup yang dituju, tanpa culas atau menipu, penuh senyum dan tawa.
Dalam sejumlah ayat Al-Quran ditegaskan, bekerja bukan sekadar aktivitas ekonomi, tapi juga bagian dari ibadah, manifestasi tanggung jawab sosial. Dalam QS Al-Jumu’ah: 10, dituturkan, usai salat Jumat manusia disilakan bertebaran di muka bumi, menjemput rezeki, membuka peluang, meyakinkan diri tentang karunia Tuhan itu nyata, dan semuanya sebagai jalan zikir yang lempang.
Ayat di atas juga menanamkan kesan bahwa keseimbangan merupakan prinsip Islam: keseimbangan antara spiritualitas dan produktivitas; material dan non material, duniawi dan ukhrawi, pasif dan aktif. Saat salat, manusia dididik prinsip totalitas dan pasif, pasrah pada Tuhan, tetapi mengakhirinya, salam ditebarkan, produktivitas menjadi lokus, dan spirit ritual dimaterialkan secara kongkrit dalam kerja ekonomi, sosial dan kemanusiaan, serta spirit berbagi sebagai jalan kemanusiaan.
Saya teringat perilaku orang-orang Kudus Kulon yang bermukim di sekitar masjid Menara. Mereka aktivis tarekat Sadzili dan sekaligus aktif dalam giat bisnis. Hidupnya melingkar: rumah, pasar dan masjid. Rumah sebagai tempat produksi aneka jenis kebutuhan hidup, pasar sebagai ruang transaksi bisnis, sedangkan masjid sebagai tempat manembah Gusti melalui tarekat Syadzili. Keseimbangan tumbuh dan mengakar dalam tradisi, menciptakan konsep Gusjigang: ngaji dan dagang. Kisah ini mengekspresikan produktivitas dalam tarekat, menampik kecurigaan orang atas tarekat yang seringkali dianggap tak produktif dan penghambat kemajuan.
Masih terkait ayat di atas, Buya Hamka menafsirkannya sebagai dorongan agar manusia tidak menjadikan agama sebagai alasan meninggalkan kerja dan hidup tak produktif. Sebaliknya, agama mengajarkan dan menekankan pentingnya produktivitas. Wahbah Zuhaili menyebut ayat ini sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang mendorong pembangunan dan kemajuan, bukan sekadar fokus pada kontemplasi. Kisah orang Kudus di atas menjadi ekspresi kongkrit beragama yang produktif dan bertarekat tanpa menampik dunia.
Beragama yang produktif, menempatkan bekerja menjadi bagian lahan ibadah. Demikian Islam mengajarkan dan ini bagian dari intinya. Orang yang tapak tangannya keras, kulitnya menghitam karena bekerja, sangatlah terhormat. Pekerjaan dan rezeki yang lahir dari tangan sendiri, dicintai Nabi. Menghidupi keluarga, dengan gigih bekerja, nilainya seperti jihad di medan laga.
Dalam bekerja, diperlukan eksplorasi, mobilitas dan produktivitas. QS. Al-Mulk: 15 melakukan peneguhan perihal ini. Sebagai makhluk berbudaya, manusia menciptakan berbagai peluang melalui kreativitas. Mobilitas, eksplorasi, dan inovasi sebagai kunci dalam kemajuan bekerja.
Nabi mengajarkan kita menghindari tidur usai salat Subuh. Karena saat itu momentum untuk mengawali bekerja, mendulang rezeki bermula. Para perempuan di Bundaran Pacet pagi itu, menghidupkan pesan Nabi tersebut dalam laku secara kongkret, menghargai hidup yang dituju, tanpa culas atau menipu, penuh senyum dan tawa.
Dalam sejumlah ayat Al-Quran ditegaskan, bekerja bukan sekadar aktivitas ekonomi, tapi juga bagian dari ibadah, manifestasi tanggung jawab sosial. Dalam QS Al-Jumu’ah: 10, dituturkan, usai salat Jumat manusia disilakan bertebaran di muka bumi, menjemput rezeki, membuka peluang, meyakinkan diri tentang karunia Tuhan itu nyata, dan semuanya sebagai jalan zikir yang lempang.
Ayat di atas juga menanamkan kesan bahwa keseimbangan merupakan prinsip Islam: keseimbangan antara spiritualitas dan produktivitas; material dan non material, duniawi dan ukhrawi, pasif dan aktif. Saat salat, manusia dididik prinsip totalitas dan pasif, pasrah pada Tuhan, tetapi mengakhirinya, salam ditebarkan, produktivitas menjadi lokus, dan spirit ritual dimaterialkan secara kongkrit dalam kerja ekonomi, sosial dan kemanusiaan, serta spirit berbagi sebagai jalan kemanusiaan.
Saya teringat perilaku orang-orang Kudus Kulon yang bermukim di sekitar masjid Menara. Mereka aktivis tarekat Sadzili dan sekaligus aktif dalam giat bisnis. Hidupnya melingkar: rumah, pasar dan masjid. Rumah sebagai tempat produksi aneka jenis kebutuhan hidup, pasar sebagai ruang transaksi bisnis, sedangkan masjid sebagai tempat manembah Gusti melalui tarekat Syadzili. Keseimbangan tumbuh dan mengakar dalam tradisi, menciptakan konsep Gusjigang: ngaji dan dagang. Kisah ini mengekspresikan produktivitas dalam tarekat, menampik kecurigaan orang atas tarekat yang seringkali dianggap tak produktif dan penghambat kemajuan.
Masih terkait ayat di atas, Buya Hamka menafsirkannya sebagai dorongan agar manusia tidak menjadikan agama sebagai alasan meninggalkan kerja dan hidup tak produktif. Sebaliknya, agama mengajarkan dan menekankan pentingnya produktivitas. Wahbah Zuhaili menyebut ayat ini sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang mendorong pembangunan dan kemajuan, bukan sekadar fokus pada kontemplasi. Kisah orang Kudus di atas menjadi ekspresi kongkrit beragama yang produktif dan bertarekat tanpa menampik dunia.
Beragama yang produktif, menempatkan bekerja menjadi bagian lahan ibadah. Demikian Islam mengajarkan dan ini bagian dari intinya. Orang yang tapak tangannya keras, kulitnya menghitam karena bekerja, sangatlah terhormat. Pekerjaan dan rezeki yang lahir dari tangan sendiri, dicintai Nabi. Menghidupi keluarga, dengan gigih bekerja, nilainya seperti jihad di medan laga.
Dalam bekerja, diperlukan eksplorasi, mobilitas dan produktivitas. QS. Al-Mulk: 15 melakukan peneguhan perihal ini. Sebagai makhluk berbudaya, manusia menciptakan berbagai peluang melalui kreativitas. Mobilitas, eksplorasi, dan inovasi sebagai kunci dalam kemajuan bekerja.
Allah menghamparkan bumi agar manusia menjelajah, mendulang, serta memanfaatkan yang ada di dalamnya, dengan cara berkeadaban, sebagai salah satu sumber penghidupan. Bumi cukup mampu memenuhi kebutuhan manusia, tapi dia akan bersimbah keluh dan peluh bisa manusia menumpahkan segala hasrat syahwat yang tiada batas.
Terkait ayat ini, Fakhruddin Al-Razi berkomentar: manusia tak boleh pasif. Ia mesti menciptakan peluang, mewujudkan mimpi. Di negara maju dan masyarakat modern, peluang menjadi kunci dan kreativitas sebagai jalan menuju kemajuan, di berbagai bidang dan sektor pekerjaan : pertanian, perdagangan, layanan jasa, maupun teknologi.
Sebagai inti kemajuan dan penciptaan lapangan pekerjaan, kreativitas berkolerasi dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Di dalamnya juga terdapat etika sosial. Ketika menafsirkan QS An-Najm: 39–41. Sayyid Qutb menyebut ayat tersebut sebagai landasan etika kerja dan keadilan sosial. Setiap orang, katanya, bertanggung jawab atas hasil usahanya, dan tidak boleh bergantung pada warisan atau belas kasihan semata, apalagi mengambil sesuatu yang bukan haknya. Oleh karena itu, mencuri, berdagang secara culas, dan tentu korupsi, atau kerja-kerja yang melahirkan kemadaratan, seperti jualan narkoba atau jualan jabatan, bukanlah bagian kreativitas.
Dari sudut pandang politik, terkait masalah dunia kerja, kebijakan penguasa selaiknya didasarkan pada kemaslahatan masyarakat sebagai hilir utama. Di dalamnya kreativitas diberi ruang dan peluang. Karena di tangan penguasa, kekuasaan dan kebijakan digenggam. Dan atas hak itu, kewajiban ditagih, dan kemaslahatan sebagai taruhan.
Pada ujung semua tindakan manusia dalam bekerja, takwa menjadi magnet dan energi dalam melahirkan rezeki. QS At-Talaq: 2–3 Tuhan mengungkapkan satu komitmen:
Terkait ayat ini, Fakhruddin Al-Razi berkomentar: manusia tak boleh pasif. Ia mesti menciptakan peluang, mewujudkan mimpi. Di negara maju dan masyarakat modern, peluang menjadi kunci dan kreativitas sebagai jalan menuju kemajuan, di berbagai bidang dan sektor pekerjaan : pertanian, perdagangan, layanan jasa, maupun teknologi.
Sebagai inti kemajuan dan penciptaan lapangan pekerjaan, kreativitas berkolerasi dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Di dalamnya juga terdapat etika sosial. Ketika menafsirkan QS An-Najm: 39–41. Sayyid Qutb menyebut ayat tersebut sebagai landasan etika kerja dan keadilan sosial. Setiap orang, katanya, bertanggung jawab atas hasil usahanya, dan tidak boleh bergantung pada warisan atau belas kasihan semata, apalagi mengambil sesuatu yang bukan haknya. Oleh karena itu, mencuri, berdagang secara culas, dan tentu korupsi, atau kerja-kerja yang melahirkan kemadaratan, seperti jualan narkoba atau jualan jabatan, bukanlah bagian kreativitas.
Dari sudut pandang politik, terkait masalah dunia kerja, kebijakan penguasa selaiknya didasarkan pada kemaslahatan masyarakat sebagai hilir utama. Di dalamnya kreativitas diberi ruang dan peluang. Karena di tangan penguasa, kekuasaan dan kebijakan digenggam. Dan atas hak itu, kewajiban ditagih, dan kemaslahatan sebagai taruhan.
Pada ujung semua tindakan manusia dalam bekerja, takwa menjadi magnet dan energi dalam melahirkan rezeki. QS At-Talaq: 2–3 Tuhan mengungkapkan satu komitmen:
"Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.”
Ayat tersebut menunjukkan pesan bahwa rezeki tidak hanya bergantung pada kerja keras, tetapi juga pada integritas dan spiritualitas. Takwa membuka pintu-pintu rizki yang tak terduga. Ibnu Katsir menekankan bahwa takwa adalah sebab datangnya pertolongan Allah. Rezeki yang halal dan berkah sering kali datang dari arah yang tidak terduga, sebagai buah dari kejujuran dan kesabaran. Takwa dalam konteks ini merupakan sikap yang kongkrit: kejujuran dan integritas.
Oleh karena itu, baik secara individu maupun dalam konteks komunal sosial dan politik, bekerja adalah bagian dari ekspresi spiritual, yang syarat utamanya adalah kompetensi dan integritas. Secara politik, orang yang tak memiliki kapasitas dan tak memilki integritas, tak laik menerima atau diberi tugas-tugas politik. Selain akan tidak amanah, dari tangannya akan lahir keculasan dan kemadaratan di masyarakat. Dalam QS Al-Qashash: 26–27, kembali kita diingatkan:
Ayat tersebut menunjukkan pesan bahwa rezeki tidak hanya bergantung pada kerja keras, tetapi juga pada integritas dan spiritualitas. Takwa membuka pintu-pintu rizki yang tak terduga. Ibnu Katsir menekankan bahwa takwa adalah sebab datangnya pertolongan Allah. Rezeki yang halal dan berkah sering kali datang dari arah yang tidak terduga, sebagai buah dari kejujuran dan kesabaran. Takwa dalam konteks ini merupakan sikap yang kongkrit: kejujuran dan integritas.
Oleh karena itu, baik secara individu maupun dalam konteks komunal sosial dan politik, bekerja adalah bagian dari ekspresi spiritual, yang syarat utamanya adalah kompetensi dan integritas. Secara politik, orang yang tak memiliki kapasitas dan tak memilki integritas, tak laik menerima atau diberi tugas-tugas politik. Selain akan tidak amanah, dari tangannya akan lahir keculasan dan kemadaratan di masyarakat. Dalam QS Al-Qashash: 26–27, kembali kita diingatkan:
“Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”
Ayat tersebut muncul dalam kisah Nabi Musa dan menjadi pedoman dalam memilih pekerja atau pemimpin. Kompetensi dan integritas adalah dua pilar utama dalam dunia kerja dengan beragam profesi. Al-Qurthubi menyebut ayat ini sebagai dasar etika profesional. Dalam konteks modern, ini bisa diterjemahkan sebagai kombinasi antara skil, profesionalitas dan spiritualitas sekaligus.
Intinya, bekerja dalam Islam bukan sekadar mencari uang, tetapi membangun peradaban, kemaslahatan, kesejahteraan sosial dan jalan ibadah. Al-Qur’an memandu umat untuk bekerja dengan semangat inovasi, profesionalitas, etika, dan spiritualitas. Tidak hanya menjadi pekerja yang produktif, tetapi juga individu yang bertakwa, kontributor bagi kemajuan dan kemaslahatan manusia dan alam semesta.
Ayat tersebut muncul dalam kisah Nabi Musa dan menjadi pedoman dalam memilih pekerja atau pemimpin. Kompetensi dan integritas adalah dua pilar utama dalam dunia kerja dengan beragam profesi. Al-Qurthubi menyebut ayat ini sebagai dasar etika profesional. Dalam konteks modern, ini bisa diterjemahkan sebagai kombinasi antara skil, profesionalitas dan spiritualitas sekaligus.
Intinya, bekerja dalam Islam bukan sekadar mencari uang, tetapi membangun peradaban, kemaslahatan, kesejahteraan sosial dan jalan ibadah. Al-Qur’an memandu umat untuk bekerja dengan semangat inovasi, profesionalitas, etika, dan spiritualitas. Tidak hanya menjadi pekerja yang produktif, tetapi juga individu yang bertakwa, kontributor bagi kemajuan dan kemaslahatan manusia dan alam semesta.