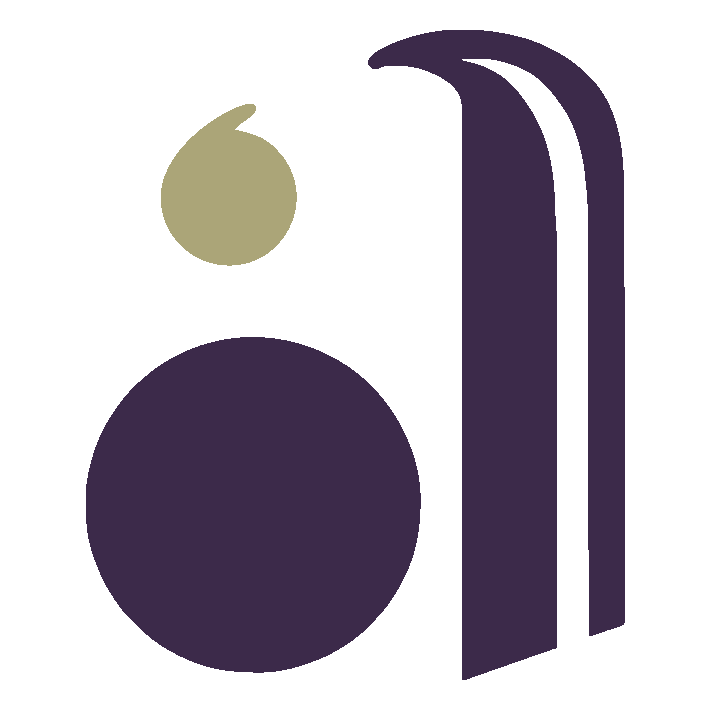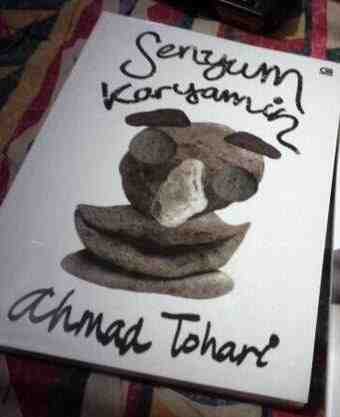Buku & Kita
|
Sejarah Indonesia
Alicia Schrikker Mengungkap Sejarah Kecil yang Hilang
Abi S Nugroho
Minggu, 24 Agustus 2025 | 02:26 WIB
Sejarah bukan cuma dimiliki pemenang, sejarah bukan cuma dimiliki orang besar di panggung-panggung besar. Orang kecil, terpinggirkan, juga berhak atas sejarah besar.

Sejarah kolonial Indonesia selama puluhan tahun ditulis dengan pola yang sama. Kisah tentang kekuasaan besar, gubernur jenderal, pertempuran, hingga kebijakan politik. Narasi yang “besar” ini kerap melupakan hal-hal yang tampak remeh. Kisah seorang bocah yang dijual sebagai budak, seorang tukang pos yang dipenjara karena salah kirim paket, atau perintah absurd seorang penjaga Belanda di kamp Boven Digoel agar tahanan politik menangkap kupu-kupu.
Alicia Schrikker dalam karyanya berjudul De vlinders van Boven-Digoel (Prometheus, 2021), mencoba melakukan pembalikan narasi. Ia menolak sejarah kolonial yang kaku, steril, dan berpusat pada penguasa, lalu mengajukan cara baca baru, sejarah mikro yang menyoroti individu biasa, dengan segala absurditas, luka, dan ketidakadilan yang mereka alami.
Upaya ini sejalan dengan tradisi sejarawan seperti Carlo Ginzburg di Eropa, atau dalam konteks Indonesia, mengingatkan pada Ong Hok Ham (1933-2007) dengan pendekatan keseharian, Takashi Shiraishi yang mengungkap dinamika pergerakan bawah tanah (Zaman Bergerak), maupun John Sidel yang menelaah akar sosial politik Asia Tenggara. Schrikker, lewat arsip kolonial yang ia gali di Jakarta dan Leiden, menghadirkan kembali cerita-cerita kecil itu dengan kekuatan narasi yang membuat pembaca tertegun.
Buku ini dibuka dengan kisah memilukan dua bocah, Tapan dan Tsjanga, yang masih di bawah sepuluh tahun ketika diculik dan dijual sebagai budak. Tidak ada pertempuran besar, tidak ada keputusan politik tinggi, hanya sebuah transaksi kejam yang memperlihatkan banalitas kolonialisme, bagaimana tubuh anak direduksi jadi komoditas.
Kisah lain menyentuh absurditas birokrasi kolonial. Oesman, seorang tukang pos, dijatuhi hukuman penjara enam bulan lantaran mengirim paket ke alamat yang salah. Di sini kita melihat bahwa kolonialisme tidak hanya menindas lewat cambuk dan senjata, melainkan juga lewat aturan administratif yang membunuh akal sehat.
Boven Digoel: Tahanan Politik dan Kupu-Kupu
Puncaknya adalah kisah Boven Digoel, kamp tahanan politik yang sudah lama dikenal sebagai simbol penindasan kolonial terhadap aktivis pergerakan. Namun Schrikker menyoroti detail unik. Seorang penjaga Belanda menyuruh tahanan menangkap kupu-kupu. Seolah-olah kupu-kupu yang indah itu bisa mengalihkan mereka dari gagasan besar tentang kemerdekaan.
Di sini, kupu-kupu jadi metafora. Rapuh, indah, bebas, tetapi juga mudah ditangkap. Ia melambangkan bagaimana kolonialisme berusaha menjinakkan manusia, sekaligus bagaimana manusia tetap bisa menemukan fragmen kebebasan meski dalam kungkungan.
Metode Schrikker jelas dipengaruhi pendekatan mikrohistori, membaca sejarah besar melalui fragmen kecil. Dengan cara ini, ia berhasil menunjukkan bahwa kolonialisme bekerja bukan hanya melalui peristiwa heroik atau kebijakan struktural, melainkan justru lewat hal-hal kecil yang menentukan nasib hidup manusia.
Dalam hal ini, karyanya mengingatkan pada Carlo Ginzburg dengan The Cheese and the Worms atau Clifford Geertz dengan etnografi “thick description”-nya. Bedanya, Schrikker menempatkan arsip kolonial sebagai titik berangkat, lalu memberi napas naratif yang membuat “orang kecil” dalam arsip itu menjadi nyata kembali.
Pendekatan ini juga memberi kritik tajam terhadap historiografi kolonial Belanda yang selama berabad-abad lebih sibuk menulis sejarah VOC, kerajaan, atau administrasi, ketimbang suara orang biasa yang jadi korban.
Resonansi dengan Historiografi Indonesia
Ketika dibandingkan dengan sejarawan Indonesia, buku ini terasa segar. Ong Hok Ham dalam berbagai esainya juga menekankan pentingnya melihat sejarah lewat praktik sehari-hari, bukan hanya narasi resmi. Takashi Shiraishi dalam Zaman Bergerak menyingkap gerakan bawah tanah, bagaimana orang kecil jadi agen perubahan. John Sidel menekankan akar sosial dan peran jaringan lokal dalam pembentukan negara-bangsa di Asia Tenggara.
Schrikker melanjutkan tradisi ini, tetapi dengan fokus pada absurditas kolonialisme yang sering terlewat. Di sinilah ia relevan bagi pembaca Indonesia. Ia memberi perspektif baru bahwa kolonialisme bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga birokrasi, hukum, dan bahkan bahasa.
Hannah Arendt pernah menyebut istilah “banality of evil” untuk menjelaskan bahwa kejahatan besar kadang lahir dari rutinitas biasa. Kolonialisme yang ditulis Schrikker persis begitu, kejahatan yang banal. Anak dijual, posmen dipenjara, kupu-kupu dijadikan alat penjinakan. Semua tampak kecil, tetapi justru di situlah kejahatan bekerja paling efektif.
Seperti kata Foucault, kekuasaan tidak selalu hadir dalam represi keras, melainkan dalam mekanisme halus yang membuat orang patuh tanpa sadar. Buku ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan kolonial menembus sampai urusan sepele, membentuk mentalitas kepatuhan, dan mengubah hidup orang biasa.
Relevansi 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia
Membaca buku terjemahan Rianti D. Manullang di tahun 2025, ketika Indonesia memasuki 80 tahun kemerdekaan, terasa sangat relevan. Pertanyaannya, apakah kita sungguh sudah merdeka?
Birokrasi yang masih menindas, kisah Oesman, tukang pos yang dipenjara karena salah alamat, seolah hidup kembali dalam birokrasi Indonesia kini. Betapa banyak warga yang terjebak dalam aturan absurd, dari pencatatan sipil yang rumit hingga kriminalisasi karena hal administratif.
Anak-anak yang hilang dalam sistem, Tapan dan Tsjanga adalah potret getir bahwa tubuh anak bisa diperlakukan sebagai komoditas. Di Indonesia hari ini, kita masih mendengar kisah pekerja anak, trafficking, dan anak-anak miskin yang tak diakui negara.
Politik penjinakan, dengan instruksi menangkap kupu-kupu di Boven Digoel mengingatkan pada cara kekuasaan hari ini meredam kritik, mengalihkan perhatian publik lewat hiburan, ritual politik, atau jargon kosong, sementara masalah struktural tetap tak terselesaikan.
Kolonialisme internal, ironisnya, setelah 80 tahun merdeka, kolonialisme sering datang bukan dari luar, melainkan dari dalam, aparat negara, elite politik, atau korporasi yang memperlakukan rakyat seperti “anak jajahan”. Di titik inilah pesan Schrikker sangat penting, kemerdekaan sejati adalah terus-menerus membebaskan diri dari logika kolonial yang menyusup ke dalam cara kita berkuasa.
Kritik terhadap buku ini bisa diarahkan pada keterbatasan awal distribusinya di Indonesia. Lama hanya tersedia dalam bahasa Belanda, padahal kisahnya adalah tentang pengalaman orang Indonesia. Baru pada 2025 tersedia terjemahan Indonesia. Meski begitu, penerjemahan ini penting, karena ia memungkinkan publik Indonesia membaca dan menafsirkan kembali sejarah kolonial dengan bahasanya sendiri.
Dari sisi metodologis, ada yang mungkin menilai pendekatan mikro terlalu fragmentaris, sehingga kehilangan gambaran besar. Namun justru di sanalah keunggulan buku ini. Ia mengingatkan kita bahwa gambaran besar hanya bermakna jika dihidupi oleh kisah kecil manusia.
De vlinders van Boven-Digoel bukan buku sejarah kolonial biasa, melainkan peringatan moral. Bahwa kemerdekaan bukanlah momen sekali jadi, tetapi proses panjang untuk membebaskan diri dari segala bentuk penindasan, baik kolonialisme Belanda, maupun kolonialisme internal yang masih bercokol.
Di usia 80 tahun kemerdekaan, bangsa Indonesia perlu bercermin. Apakah kita masih mengulang kolonialisme dalam bentuk baru, atau sudah belajar dari sejarah kecil yang ditulis Schrikker? Apakah kita masih menangkap kupu-kupu, atau sudah membiarkannya terbang bebas?
Buku ini layak dibaca tidak hanya oleh sejarawan, tetapi juga oleh setiap warga negara yang ingin memahami arti kemerdekaan secara lebih dalam. Sebab, seperti yang ditunjukkan Schrikker, kemerdekaan sejati adalah ketika suara-suara kecil tak lagi dibungkam, melainkan diakui sebagai bagian penting dari sejarah bangsanya sendiri. "Merdeka 100%," kata Tan Malaka.
Alicia Schrikker dalam karyanya berjudul De vlinders van Boven-Digoel (Prometheus, 2021), mencoba melakukan pembalikan narasi. Ia menolak sejarah kolonial yang kaku, steril, dan berpusat pada penguasa, lalu mengajukan cara baca baru, sejarah mikro yang menyoroti individu biasa, dengan segala absurditas, luka, dan ketidakadilan yang mereka alami.
Upaya ini sejalan dengan tradisi sejarawan seperti Carlo Ginzburg di Eropa, atau dalam konteks Indonesia, mengingatkan pada Ong Hok Ham (1933-2007) dengan pendekatan keseharian, Takashi Shiraishi yang mengungkap dinamika pergerakan bawah tanah (Zaman Bergerak), maupun John Sidel yang menelaah akar sosial politik Asia Tenggara. Schrikker, lewat arsip kolonial yang ia gali di Jakarta dan Leiden, menghadirkan kembali cerita-cerita kecil itu dengan kekuatan narasi yang membuat pembaca tertegun.
Buku ini dibuka dengan kisah memilukan dua bocah, Tapan dan Tsjanga, yang masih di bawah sepuluh tahun ketika diculik dan dijual sebagai budak. Tidak ada pertempuran besar, tidak ada keputusan politik tinggi, hanya sebuah transaksi kejam yang memperlihatkan banalitas kolonialisme, bagaimana tubuh anak direduksi jadi komoditas.
Kisah lain menyentuh absurditas birokrasi kolonial. Oesman, seorang tukang pos, dijatuhi hukuman penjara enam bulan lantaran mengirim paket ke alamat yang salah. Di sini kita melihat bahwa kolonialisme tidak hanya menindas lewat cambuk dan senjata, melainkan juga lewat aturan administratif yang membunuh akal sehat.
Boven Digoel: Tahanan Politik dan Kupu-Kupu
Puncaknya adalah kisah Boven Digoel, kamp tahanan politik yang sudah lama dikenal sebagai simbol penindasan kolonial terhadap aktivis pergerakan. Namun Schrikker menyoroti detail unik. Seorang penjaga Belanda menyuruh tahanan menangkap kupu-kupu. Seolah-olah kupu-kupu yang indah itu bisa mengalihkan mereka dari gagasan besar tentang kemerdekaan.
Di sini, kupu-kupu jadi metafora. Rapuh, indah, bebas, tetapi juga mudah ditangkap. Ia melambangkan bagaimana kolonialisme berusaha menjinakkan manusia, sekaligus bagaimana manusia tetap bisa menemukan fragmen kebebasan meski dalam kungkungan.
Metode Schrikker jelas dipengaruhi pendekatan mikrohistori, membaca sejarah besar melalui fragmen kecil. Dengan cara ini, ia berhasil menunjukkan bahwa kolonialisme bekerja bukan hanya melalui peristiwa heroik atau kebijakan struktural, melainkan justru lewat hal-hal kecil yang menentukan nasib hidup manusia.
Dalam hal ini, karyanya mengingatkan pada Carlo Ginzburg dengan The Cheese and the Worms atau Clifford Geertz dengan etnografi “thick description”-nya. Bedanya, Schrikker menempatkan arsip kolonial sebagai titik berangkat, lalu memberi napas naratif yang membuat “orang kecil” dalam arsip itu menjadi nyata kembali.
Pendekatan ini juga memberi kritik tajam terhadap historiografi kolonial Belanda yang selama berabad-abad lebih sibuk menulis sejarah VOC, kerajaan, atau administrasi, ketimbang suara orang biasa yang jadi korban.
Resonansi dengan Historiografi Indonesia
Ketika dibandingkan dengan sejarawan Indonesia, buku ini terasa segar. Ong Hok Ham dalam berbagai esainya juga menekankan pentingnya melihat sejarah lewat praktik sehari-hari, bukan hanya narasi resmi. Takashi Shiraishi dalam Zaman Bergerak menyingkap gerakan bawah tanah, bagaimana orang kecil jadi agen perubahan. John Sidel menekankan akar sosial dan peran jaringan lokal dalam pembentukan negara-bangsa di Asia Tenggara.
Schrikker melanjutkan tradisi ini, tetapi dengan fokus pada absurditas kolonialisme yang sering terlewat. Di sinilah ia relevan bagi pembaca Indonesia. Ia memberi perspektif baru bahwa kolonialisme bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga birokrasi, hukum, dan bahkan bahasa.
Hannah Arendt pernah menyebut istilah “banality of evil” untuk menjelaskan bahwa kejahatan besar kadang lahir dari rutinitas biasa. Kolonialisme yang ditulis Schrikker persis begitu, kejahatan yang banal. Anak dijual, posmen dipenjara, kupu-kupu dijadikan alat penjinakan. Semua tampak kecil, tetapi justru di situlah kejahatan bekerja paling efektif.
Seperti kata Foucault, kekuasaan tidak selalu hadir dalam represi keras, melainkan dalam mekanisme halus yang membuat orang patuh tanpa sadar. Buku ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan kolonial menembus sampai urusan sepele, membentuk mentalitas kepatuhan, dan mengubah hidup orang biasa.
Relevansi 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia
Membaca buku terjemahan Rianti D. Manullang di tahun 2025, ketika Indonesia memasuki 80 tahun kemerdekaan, terasa sangat relevan. Pertanyaannya, apakah kita sungguh sudah merdeka?
Birokrasi yang masih menindas, kisah Oesman, tukang pos yang dipenjara karena salah alamat, seolah hidup kembali dalam birokrasi Indonesia kini. Betapa banyak warga yang terjebak dalam aturan absurd, dari pencatatan sipil yang rumit hingga kriminalisasi karena hal administratif.
Anak-anak yang hilang dalam sistem, Tapan dan Tsjanga adalah potret getir bahwa tubuh anak bisa diperlakukan sebagai komoditas. Di Indonesia hari ini, kita masih mendengar kisah pekerja anak, trafficking, dan anak-anak miskin yang tak diakui negara.
Politik penjinakan, dengan instruksi menangkap kupu-kupu di Boven Digoel mengingatkan pada cara kekuasaan hari ini meredam kritik, mengalihkan perhatian publik lewat hiburan, ritual politik, atau jargon kosong, sementara masalah struktural tetap tak terselesaikan.
Kolonialisme internal, ironisnya, setelah 80 tahun merdeka, kolonialisme sering datang bukan dari luar, melainkan dari dalam, aparat negara, elite politik, atau korporasi yang memperlakukan rakyat seperti “anak jajahan”. Di titik inilah pesan Schrikker sangat penting, kemerdekaan sejati adalah terus-menerus membebaskan diri dari logika kolonial yang menyusup ke dalam cara kita berkuasa.
Kritik terhadap buku ini bisa diarahkan pada keterbatasan awal distribusinya di Indonesia. Lama hanya tersedia dalam bahasa Belanda, padahal kisahnya adalah tentang pengalaman orang Indonesia. Baru pada 2025 tersedia terjemahan Indonesia. Meski begitu, penerjemahan ini penting, karena ia memungkinkan publik Indonesia membaca dan menafsirkan kembali sejarah kolonial dengan bahasanya sendiri.
Dari sisi metodologis, ada yang mungkin menilai pendekatan mikro terlalu fragmentaris, sehingga kehilangan gambaran besar. Namun justru di sanalah keunggulan buku ini. Ia mengingatkan kita bahwa gambaran besar hanya bermakna jika dihidupi oleh kisah kecil manusia.
De vlinders van Boven-Digoel bukan buku sejarah kolonial biasa, melainkan peringatan moral. Bahwa kemerdekaan bukanlah momen sekali jadi, tetapi proses panjang untuk membebaskan diri dari segala bentuk penindasan, baik kolonialisme Belanda, maupun kolonialisme internal yang masih bercokol.
Di usia 80 tahun kemerdekaan, bangsa Indonesia perlu bercermin. Apakah kita masih mengulang kolonialisme dalam bentuk baru, atau sudah belajar dari sejarah kecil yang ditulis Schrikker? Apakah kita masih menangkap kupu-kupu, atau sudah membiarkannya terbang bebas?
Buku ini layak dibaca tidak hanya oleh sejarawan, tetapi juga oleh setiap warga negara yang ingin memahami arti kemerdekaan secara lebih dalam. Sebab, seperti yang ditunjukkan Schrikker, kemerdekaan sejati adalah ketika suara-suara kecil tak lagi dibungkam, melainkan diakui sebagai bagian penting dari sejarah bangsanya sendiri. "Merdeka 100%," kata Tan Malaka.