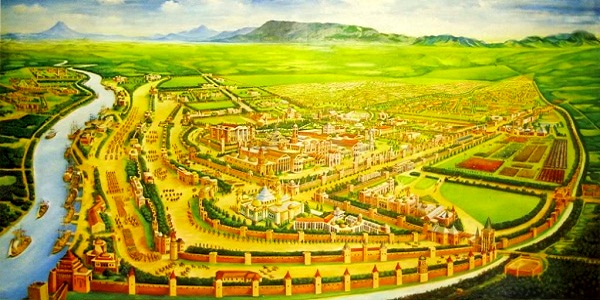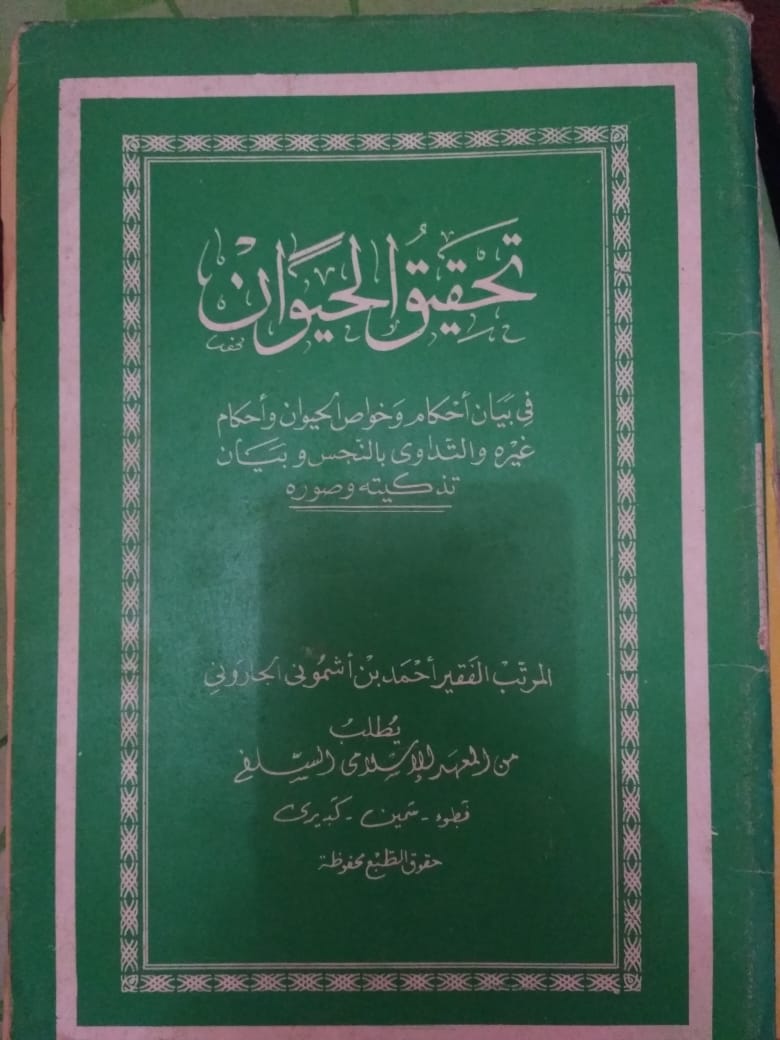Eling lan Waspada: Mistik Jawa di Tengah Modernitas
Walaupun di era yang serba digital, mistik jawa selalu menemukan relevansinya. Ia justru makin hidup di tengah derasnya arus informasi dan kecanggihan teknologi.

Mistik Jawa, dengan segala kompleksitasnya, bukan sekadar warisan masa lalu yang terpinggirkan, melainkan sistem pengetahuan yang mengandung nilai-nilai filosofis mendalam. Pada era digital, ketika manusia semakin teralienasi dari dirinya sendiri dan lingkungannya, mistik Jawa menawarkan jalan untuk menemukan kembali keseimbangan antara manusia, alam, dan teknologi.
Mistik Jawa, atau yang sering disebut sebagai kejawen, adalah sebuah sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang berakar pada harmoni kosmis. Konsep Rukun, Slamet, dan Manunggaling Kawula Gusti (bersatunya hamba dengan Tuhan) adalah inti dari filosofi ini. Dalam pandangan kejawen, manusia bukanlah entitas yang terpisah dari alam semesta, melainkan bagian integral dari sebuah kesatuan yang lebih besar.
Konsep ini mengingatkan kita pada pemikiran filsuf Barat, Martin Heidegger, yang dalam Being and Time (1927) mengkritik modernitas yang telah memisahkan manusia dari Being (Ada). Heidegger melihat bahwa manusia modern telah kehilangan hubungan otentik dengan dirinya sendiri dan alam, terperangkap dalam das Man (kehidupan sehari-hari yang teralienasi). Mistik Jawa, dengan penekanannya pada kesatuan kosmis, bisa menjadi penawar bagi krisis eksistensial yang dihadapi manusia modern.
Namun, bagaimana mungkin mistik Jawa, yang sering dianggap sebagai bagian dari dunia pra-modern, dapat menemukan relevansinya dalam era digital? Jawabannya terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dan berintegrasi dengan realitas baru. Era digital, dengan segala kemudahan dan kompleksitasnya, telah menciptakan paradoks: di satu sisi, teknologi memungkinkan manusia untuk terhubung secara global, tetapi di sisi lain, ia juga menciptakan jarak yang semakin lebar antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya.
Di sinilah mistik Jawa menawarkan sebuah alternatif. Konsep Slamet, misalnya, yang berarti keselamatan dan keseimbangan, bisa diterapkan dalam konteks penggunaan teknologi. Dalam dunia yang dipenuhi informasi berlebihan (information overload), prinsip Slamet mengajarkan kita untuk selektif dan bijak dalam mengonsumsi informasi, sehingga tidak terjebak dalam kecemasan dan kebingungan.
Filsuf Muslim, Ibn Arabi, dalam karyanya Fusus al-Hikam (Permata-permata Kebijaksanaan), juga menawarkan pandangan yang selaras dengan mistik Jawa. Ia berbicara tentang Wahdat al-Wujud (Kesatuan Wujud), sebuah konsep yang menekankan bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah manifestasi dari Tuhan. Dalam konteks era digital, konsep ini bisa diartikan sebagai pengakuan bahwa teknologi, sebagai produk manusia, juga merupakan bagian dari kesatuan kosmis.
Dengan demikian, teknologi tidak harus dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai alat yang bisa digunakan untuk mencapai harmoni. Namun, Ibn Arabi juga mengingatkan bahwa manusia harus selalu sadar akan batas-batasnya. Dalam dunia digital yang serba cepat, kesadaran ini menjadi penting agar kita tidak terjebak dalam ilusi kemahakuasaan teknologi.
Sementara itu, filsuf Barat, Jean Baudrillard, dalam Simulacra and Simulation (1981), mengkritik modernitas yang telah menciptakan dunia hiper-realitas, di mana batas antara yang nyata dan yang maya semakin kabur. Baudrillard melihat bahwa manusia modern hidup dalam dunia yang dipenuhi oleh simulasi, di mana pengalaman otentik semakin langka. Mistik Jawa, dengan penekanannya pada pengalaman langsung dan kesadaran penuh (eling lan waspada), bisa menjadi penangkal bagi hiper-realitas ini.
Dalam praktik meditasi dan laku spiritual Jawa, misalnya, individu diajak untuk menyadari keberadaannya di sini dan saat ini (here and now), sebuah konsep yang juga ditemukan dalam tradisi Zen Buddhisme. Dalam era digital, di mana perhatian kita sering terpecah-pecah oleh berbagai distraksi, praktik semacam ini menjadi semakin penting.
Namun, integrasi mistik Jawa dalam era digital tidak berarti mengabaikan kritik terhadap modernitas. Filsuf Jerman, Jürgen Habermas, dalam The Theory of Communicative Action (1981), mengingatkan kita bahwa modernitas memiliki potensi untuk membebaskan manusia dari belenggu tradisi yang tidak rasional. Namun, Habermas juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara rasionalitas instrumental (yang mendominasi dunia modern) dan rasionalitas komunikatif (yang memungkinkan dialog dan pemahaman antar-manusia).
Mistik Jawa, dengan segala kekayaan spiritualnya, bisa menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan keseimbangan ini. Dalam konteks ini, mistik Jawa tidak harus dilihat sebagai lawan dari modernitas, melainkan sebagai mitra yang bisa melengkapi dan memperkaya pemahaman kita tentang dunia.
Dalam praktiknya, integrasi mistik Jawa dalam era digital bisa mengambil berbagai bentuk. Misalnya, dalam dunia pendidikan, nilai-nilai kejawen seperti ngeli ning ora keli (mengalir tanpa hanyut) bisa diajarkan sebagai cara untuk menghadapi tantangan dunia digital. Prinsip ini mengajarkan kita untuk tetap fleksibel dan adaptif, tanpa kehilangan jati diri. Di sisi lain, dalam dunia bisnis, konsep gotong royong (kerja sama) bisa menjadi alternatif bagi model kompetisi yang sering kali merugikan.
Dalam dunia seni dan budaya, mistik Jawa bisa menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan karya-karya yang tidak hanya estetis, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual. Dalam konteks ini, mistik Jawa harus dipahami sebagai sebuah sistem pengetahuan yang dinamis, yang terus berkembang dan beradaptasi dengan konteks zamannya. Dengan demikian, mistik Jawa tidak akan menjadi fosil yang terkurung dalam museum, melainkan sebuah kekuatan hidup yang bisa memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan manusia modern.
Pada akhirnya, mistik Jawa dan modernitas bukanlah dua kutub yang bertentangan, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama. Dalam era digital, di mana manusia semakin teralienasi dari dirinya sendiri dan lingkungannya, mistik Jawa menawarkan sebuah jalan untuk menemukan kembali keseimbangan dan harmoni.
Dengan menggali nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam mistik Jawa, kita tidak hanya bisa menghadapi tantangan zaman dengan lebih bijak, tetapi juga menciptakan sebuah dunia yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Seperti kata Rumi, seorang sufi besar, “Kamu bukanlah setetes air di lautan, kamu adalah seluruh lautan dalam setetes air.” Dalam konteks ini, mistik Jawa mengajarkan kita bahwa di tengah gempuran modernitas, kita tetap bisa menemukan kedalaman dan makna dalam setiap aspek kehidupan.