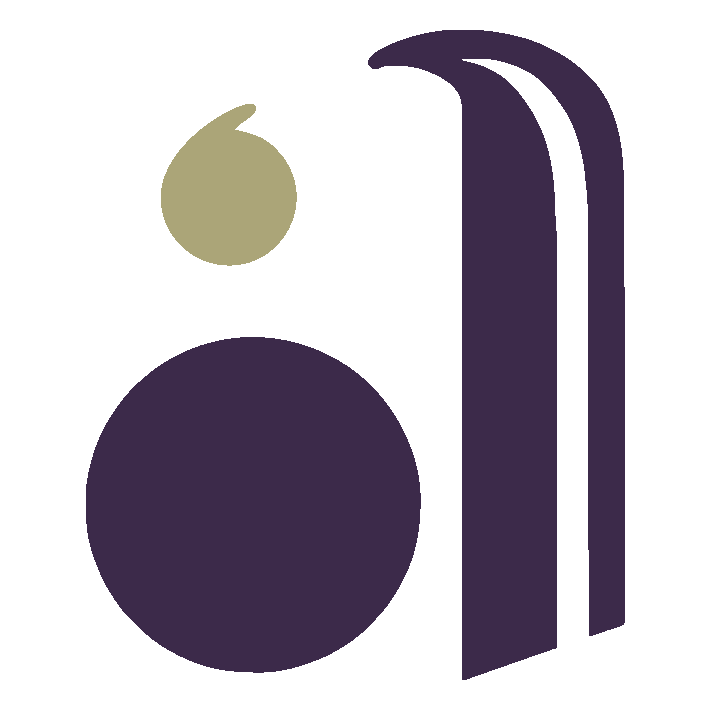Ia dilahirkan sebelum Indonesia diproklamasikan: 10 Agustus 1944. Kelahiran atas nama bapak dan ibu berharap bahagia. Pada 1987, ia menggubah puisi perkenalan diri berjudul “Identitas Atawa Aku dalam Angka”.
Kita sedikit mengetahui sosok asal Rembang: namaku mustofa bin bisri mustofa/ lahir sebelum masa anak cukup 2/ sebagai anak ke 2 dari 9 bersaudara. Kita akrab dengan panggilan Gus Mus. Di penghormatan religius, pencantuman berbeda: KH A Mustofa Bisri. Masalah nama itu dipuisikan dengan judul “Mula-Mula”. Kita membaca: Mula-mula mereka beri aku nama/ Lalu dengan nama itu/ Mereka belenggu tangan dan kakiku. Kita mengisanfi itu kelakar atas nasib anak diberi nama oleh orangtua. Kita mengerti nama bapak (Bisri Mustofa) dan nama anak (Mustofa Bisri).
Kita cukupkan perkenalan tokoh. Kita urusi saja masalah usia Gus Mus dan Indonesia (merdeka). Kita pun ingin mengingat tanggapan-tanggapan Gus Mus atas lakon Indonesia melalui puisi-puisi masa lalu, bukan puisi baru. Kita sedang memperingati 81 tahun Gus Mus sambil mengutip puisi-puisi untuk peringatan 80 tahun Hari Kemerdekaan Indonesia. Gus Mus termasuk rajin memasalahkan Indonesia dalam ratusan puisi. Kita pilih-pilih saja sembarangan asal puisi pantas ditafsirkan (kembali) sesuai situasi Indonesia mutakhir atau sekadar mengenang Indonesia masa Orde Baru.
Kita terkejut saat membaca lagi puisi Gus Mus mengenai Pancasila. Ia mengingat dan berseru Pancasila berlatar Orde Baru. Konon, rezim bertuan Soeharto menggunakan represi atau kekerasan dalam mencipta insan-insan wajib Pancasilais. Pelbagai kebijakan dibuat agar Soeharto terbukti memuliakan Pancasila ketimbang rezim terdahulu. Kita ikut mengingat kebijakan terpenting Orde Baru: Penataran P-4.
Pada 1983, Gus Mus menggubah “Sajak Dor Dor Hure Dua”. Puisi bila dibaca di panggung terasakan keras dan mengecam. Kita mengutip: Dor!/ Hidup Ketuhanan Yang Maha Esa!/ Dor! Dor!/ Hidup Kemanusiaan yang Adil dan Beradab! Dor! Dor! Dor! Hidup Persatuan Indonesia!/ Dor! Dor! Dor! Dor!/ Hidup Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan!/ Dor! Dor! Dor! Dor! Dor!/ Hidup Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia/ Dor!/ Dor!/ Dor Pancasila!/ Dor!/Dor! Puisi membuka lembaran sejarah saat rezim menggunakan senapan atau bedil dalam mencipta ketertiban dan kepatuhan. Pada masa 1980-an, kita mengingat orang-orang bertato mati di pelbagai tempat. Pertunjukkan mengerikan dan politis agar orang-orang taat kepada Soeharto. Pancasila digunakan untuk “mendidik” dan “mendikte”. Masa lalu mengisahkan “penembakan misterius”.
Kini, Gus Mus berusia 81 tahun. Kita belum mengetahui puisi-puisi baru. Apakah ia masih mau menulis puisi atau memilih menikmati hari tua dengan peristiwa-peristiwa enteng tanpa beban estetika dan politik? Kita menunggu jika ada puisi-puisi baru sambil membaca lagi puisi lama berjudul “Nyanyian Kebebasan Atawa Boleh Apa Saja.” Ia sedang mengartikan merdeka. Kita membaca menjelang peringatan Hari Kemerdekaan: 17 Agustus 2025.
Gus Mus menulis: Ohoi,/ Politikus boleh berlagak kiai/ Kiai boleh main film semau hati/ Ilmuwan boleh menggugat ayat/ Gelandangan boleh mewakili rakyat. Puisi diawali pekik: “Merdeka!” Sejak 17 Agustus 1945, kita sering “salah” dan “sembrono” mengartikan merdeka. Dulu, “merdeka” itu kehendak besar untuk merampungkan kolonialisme. “Merdeka” memang masih salah tafsir sejak 1945 tapi kata itu menguatkan revolusi. Pada masa Orde Baru, pengertian “merdeka” makin tak keruan. Gus Mus menulis “merdeka” dalam keamburadulan Indonesia pada 1987.
Pada masa Orde Baru, Gus Mus rajin menulis puisi-puisi mengandung kritik, gugatan, dan lelucon. Ia menganggap demokrasi di Indonesia salah kiblat. Para pejabat dan orang-orang di gedung parlemen mengaku kaum paling penting. Mereka minta dimanjakan, dihormati, dan dipatuhi. Cara tergampang pamer kekuasaan masa lalu dengan rajin berpidato. Kita mengingat pidato-pidato menjemukan dan memberi “siksa bahasa”
Di puisi berjudul “Agitasi Atawa Pidato Rakyat Jelata di Depan Oknum Pemimpin dan Pejabat.” Ia membalik posisi. Orang-orang berkuasa diminta mendengarkan pidato, tak boleh mengantuk atau bodoh. Pidato dari jelata wajib dinikmati secara serius. Gus Mus memberi lelucon: Bapak-bapak, ibu-ibu panutan kamu/ Para pemimpin dan pejabat yang terhormat/ Sebelumnya maafkanlah kami/ Kami sudah sering bapak-bapak dan ibu-ibu pidatokan/ Terima kasih nama kamu telah bapak-bapak dan ibu-ibu bawa/ Ke mana-mana pada setiap kesempatan/ Jika bapak-bapak dan ibu-ibu berkenan, o panutan kami/ Kini kami ingin bicara sendiri untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Kritik keras melalui pembalikkan posisi dalam pidato. Orde Baru terbukti “orde pidato” atas nama pembangunanisme.
Gus Mus pasti paham bila para pejabat dan pemimpin di rezim Prabowo-Gibran pun suka omong, pamer pidato, dan mengumbar janji-janji bergelimang ilusi. Rezim mau tegak dengan pidato. Di posisi jelata ingin omong, segala risiko wajib ditanggung. Kita memang tak menantikan kaum jelata pidato saat Indonesia kelelahan oleh berita-berita buruk. Pidato medingan digantikan gosip dan permainan teka-teki tanpa jawaban benar.
Kita mengandaikan Gus Mus memasang puisi baru di media sosial mengenai 80 tahun Indonesia merdeka. Puisi mungkin lucu atau sadis. Para pembaca boleh mengangguk atau geleng kepala saat menghubungkan puisi dengan politik mutakhir. Gus Mus pun berhak tak menulis dan mengunggah puisi. Ia tak diwajibkan terus berpuisi meski telah memberi ratusan puisi kita pelajari saat rezim-rezim berganti.
Puisi lama menanggapi tatanan kekuasaan. Gus Mus memberi puisi berjudul “Di Negerimu”, bermaksud kita sadar Indonesia terlalu bermasalah: Inilah negeri paling aneh/ Negeri adiluhung yang mengimpor majikan asing dan sampah/ Negeri berbudaya yang mengekspor babu-babu dan asap/ Negeri yang sangat sukses menemukan kambing hitam/ dan tikus-tikus/ Negeri yang angkuh dengan utang-utang yang tak terbayar/ Negeri teka-teki penuh misteri. Gus Mus sedang mengisahkan Indonesia, bukan negeri-negeri di benua berbeda. Sekian larik masih cocok untuk Indonesia sekarang. Puisi tak bermaksud menjadi ramalan tapi Gus Mus memiliki kepekaan agar puisi awet sepanjang masa.
Pada 1997, menjelang keruntuhan rezim Orde Baru, Gus Mus menggubah puisi berjudul “Negeri Teka-Teki.” Ia menggoda pembaca agar mau dan berhasil menemukan jawaban. Puisi agak lucu tapi tragis: Jangan tanya mengapa/ Yang di sini selalu dibenarkan/ Yang di sana selalu disalahkan, tebak saja!// Jangan tanya siapa/ Membakar hutan dan emosi rakyat/ Siapa melindungi penjahat keparat/ Jangan tanya mengapa, tebak saja!// Jangan tanya mengapa/ setiap kali terjadi kekeliruan/ pertanggyngjawaban tak keruan/ Tebak saja! Hidup di Indonesia penuh teka-teki. Jawaban benar dan salah sulit dibedakan saat penguasa ingin selalu menang. Kita diajak mengingat babak akhir rezim Soeharto sambil mencari persamaan-persamaan dengan lakon Indonesia abad XXI. Segala teka-teki masih menunggu jawaban. Konon jawaban sudah ada tapi “terlarang” belum diumumkan.
Kini, kita membaca ulang puisi terus ditulis dengan penjudulan “Rasanya Baru Kemarin”. Kita membaca edisi gubahan 17 Agustus 2000. Gus Mus mengungkapkan: Banyak orang pandai sudah semakin linglung/ Banyak orang bodoh sudah semakin bingung/ Banyak orang kaya sudah semakin kekurangan. Banyak orang miskin sudah semakin kecurangan. Kita anjurkan larik-larik puisi tak perlu dikaitkan penjelasan pejabat pandai: makanan bergizi gratis berdampak meningkatkan kemampuan murid dalam matematika dan bahasa Inggris. Keterangan justru membuat kita berhadapan teka-teki mustahil terjawab. Puisi gubahan Gus Mus itu sulit dikaitkan dengan teka-teki dibuat oleh sosok pintar berada dalam kabinet Prabowo.
Kita lanjutkan membaca edisi ditulis 17 Agustus 2002. Gus Mus tetap tekun membaca dan menilai Indonesia. Ia menulis: Hari ini/ setelah limapuluh tujuh tahun kita merdeka/ ingin rasanya aku mengajak kembali/ mereka semua yang kucinta/ untuk mensyukuri lebih dalam/ rahmat kemerdekaan ini. Kita pun menunggu muncul edisi puisi ditulis 17 Agustus 2025. Kita berharap Gus Mus masih berpuisi meski menua. Begitu.