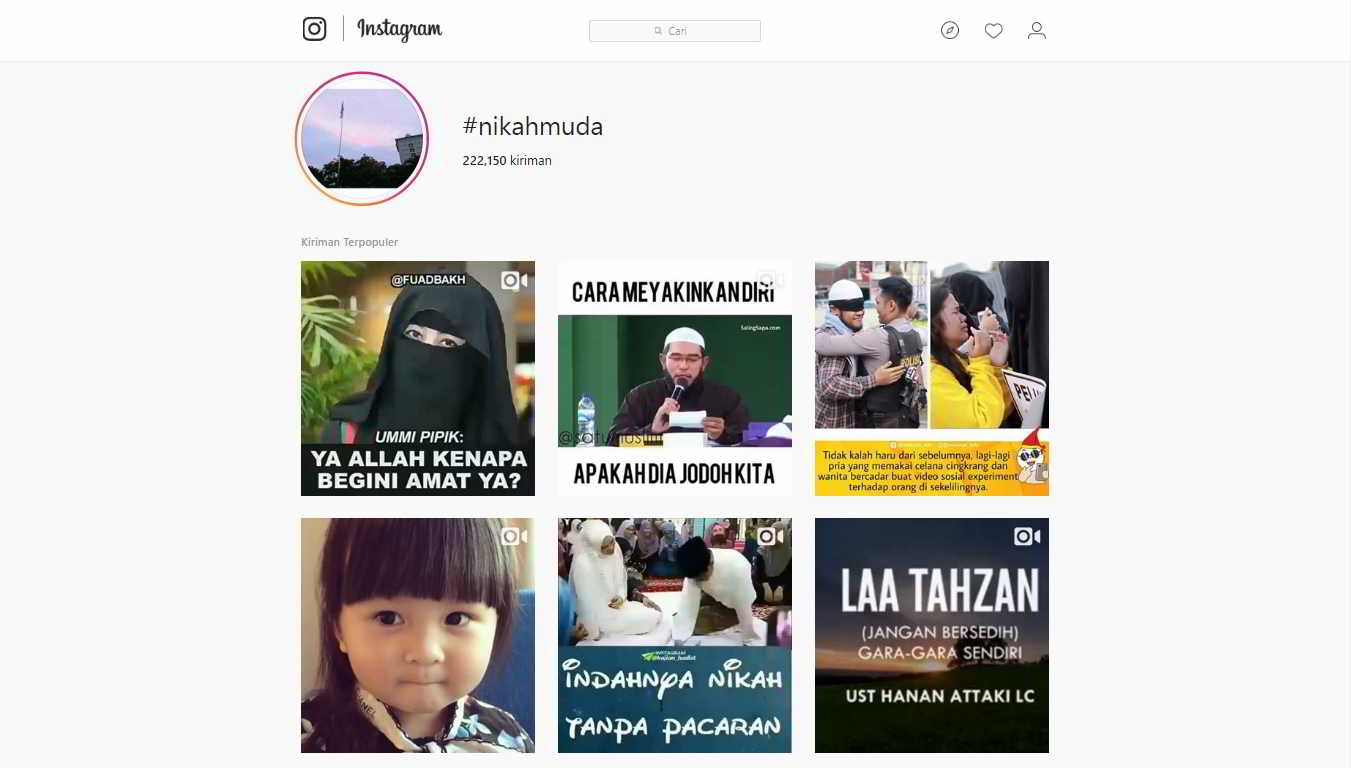Religiositas Tubuh Perempuan di Garis Depan Melawan Kekuasaan
Ketika kita melihat perempuan berani bersuara dan turun ke jalan atas kebijakan pemerintah, sebenarnya kita tengah menyaksikan spiritualitas yang berwujud pada kasih dan perhatian.

Hiruk pikuk demonstrasi besar yang melanda kota-kota Indonesia dalam akhir Agustus kemarin, ada dokumentasi peristiwa yang kerap kita saksikan di media massa dan media sosial. Tergambar satu pemandangan yang kontras di mana ibu-ibu berdiri di garis depan, berhadapan langsung dengan aparat kepolisian yang lengkap dengan tameng, helm, dan gas air mata, yang membentuk barisan siap maju.
Rekaman peristiwa konfrontasi ini menyingkap pertarungan yang jauh lebih dalam ketimbang sekadar protes politik. Sebuah benturan antara tubuh rapuh dengan mesin kekuasaan maskulin, antara kerentanan dengan represi, antara spiritualitas dengan nalar kekerasan negara.
Fenomena ini mengundang pembacaan filosofis. Sebab, di balik tubuh-tubuh perempuan yang hadir di jalanan, kita menemukan dimensi spiritualitas dan religiositas yang kerap terabaikan dalam analisis politik. Mereka bukan hanya “demonstran”, melainkan simbol dari horizon etis yang melampaui kalkulasi strategis.
Dimensi Religiositas
Simone Weil, seorang filsuf mistik Prancis, dalam Waiting for God (1950) menulis bahwa kerentanan manusia adalah pintu masuk menuju spiritualitas sejati. Bagi Weil, “attention to the other”—perhatian murni kepada yang lain—adalah inti dari pengalaman religius.
Kehadiran ibu-ibu di garis depan, dengan tanpa pelindung selain keyakinan mereka, adalah bentuk paling telanjang dari kerentanan itu. Tapi justru kerentanan inilah yang menyingkap kekuatan moral. Dengan hadir, mereka menunjukkan perhatian kepada nasib bersama yang dialami, yaitu tentang anak-anak yang lapar, harga-harga yang mencekik, dan keadilan yang dirampas – sesuatu yang dialami, dihadapi dan (oleh karenanya lalu) diperjuangkan.
Gambaran ini selaras dengan etika wajah Emmanuel Levinas dalam Totality and Infinity (1961). Bagi Levinas, wajah orang lain (yang rapuh, terbuka, tanpa perlindungan) menyampaikan seruan etis: “Engkau tidak boleh membunuh.” Dalam logika ini, tubuh perempuan yang berdiri di hadapan aparat adalah wajah yang memanggil kesadaran moral negara.
Namun, alih-alih mendengar, negara justru menutup telinga, membungkam suara, dan mengerahkan represi. Di sini, religiositas yang diklaim negara terkuak sebagai retorika kosong, sebab wajah manusia di jalanan tidak dihormati.
Sementara itu, Paul Ricoeur dalam Oneself as Another (1990) menekankan bahwa identitas etis manusia dibangun dalam narasi tanggung jawab. Perempuan yang hadir di garis depan sedang menulis narasi alternatif bahwa keberanian bukan monopoli kekuasaan bersenjata, melainkan tanggung jawab moral yang lahir dari keterikatan pada kelompok terdekat: keluarga, komunitas, kelas. Mereka menghadirkan etika naratif berupa kisah tentang kasih, pengorbanan, dan solidaritas yang menandingi kisah resmi negara tentang keamanan dan stabilitas.
Dimensi religiositas dari tindakan ini juga tampak jelas jika kita memakai kacamata filsuf Kanada Charles Taylor. Dalam buku Sources of the Self (1989), Taylor menulis bahwa manusia selalu mencari horizon makna yang melampaui kepentingan pragmatis. Ketika tubuh perempuan menghadang kendaraan aparat, yang dipertaruhkan bukan sekadar tuntutan politik sesaat, tetapi horizon moral seperti martabat, kehidupan yang layak, dan keadilan sosial. Keberanian mereka lahir dari keyakinan bahwa ada “kebaikan lebih besar” yang melampaui kalkulasi kekuasaan.
Dehumanisasi Modern
Lebih jauh, Seyyed Hossein Nasr dalam Religion and the Order of Nature (1996) mengingatkan bahwa spiritualitas juga merupakan kritik terhadap dehumanisasi modern. Negara modern sering terjebak dalam logika teknologi, administrasi, dan kontrol yang meniadakan martabat manusia. Aparat dengan senjata dan teknologi pengendalian massa adalah ekspresi konkret dari dehumanisasi itu.
Namun tubuh rapuh perempuan mengingatkan kita pada tatanan spiritual, bahwa manusia adalah makhluk sakral, bukan sekadar angka dalam laporan keamanan. Spiritualitas perempuan di garis depan tidak hanya melawan represi eksternal, tetapi juga mengganggu asumsi internal masyarakat.
Dalam banyak tradisi religius, perempuan kerap ditempatkan pada posisi domestik. Namun, kehadiran mereka di jalanan menegaskan bahwa religiositas sejati tidak berhenti pada ruang privat, melainkan meresap ke dalam ruang publik. Tubuh mereka menjadi simbol liturgi perlawanan, serupa sebuah doa yang diucapkan bukan dengan kata, melainkan dengan langkah kaki dan keberanian.
Fenomena ini juga menguak paradoks moral bangsa. Indonesia sering memuji diri sebagai bangsa religius. Namun, di saat yang sama, aparat negara bisa dengan enteng memukul, melindas dan menindas tubuh-tubuh rapuh itu.
Apakah religiositas hanya berhenti pada ritual formal, sementara inti etisnya berupa perhatian pada penderitaan sesama, diabaikan? Dengannya, apa arti doa jika kita menutup mata pada derita orang lain?
Melalui tubuh perempuan, kita diajak melihat bahwa kekuatan moral jauh lebih besar daripada kekuatan represif. Aparat dengan tameng mungkin bisa menahan laju demonstran, tetapi tidak bisa menahan gelombang makna yang lahir dari kerentanan. Seperti ditegaskan Ricoeur, narasi etis memiliki kekuatan yang melampaui kekerasan.
Pada titik ini, demonstrasi dapat dibaca sebagai “liturgi sosial”, sebuah ibadah kolektif di jalanan. Liturgi ini tidak berbentuk doa ritual, tetapi terwujud dalam solidaritas, keberanian, dan kerelaan untuk mempertaruhkan diri demi sesama, demi kebaikan bersama, demi kebenaran hakiki yang sedang ditindas. Religiusitas di sini bukan lagi dogma, melainkan praksis etis yang hidup.
Maka, ketika kita menyaksikan tubuh perempuan berhadapan dengan aparat, kita sebenarnya sedang menyaksikan pertarungan dua jenis spiritualitas, yaitu spiritualitas kerentanan yang berakar pada kasih dan perhatian, melawan spiritualitas palsu yang dibungkus retorika keamanan.
Maka, apakah kita masih berani menyebut diri bangsa religius, bila wajah rapuh di jalanan dibiarkan dipukul, digas, bahkan dilindas? Apakah religiositas hanya berhenti di bibir doa, ataukah ia hidup dalam keberanian untuk memberi perhatian penuh kasih pada tubuh-tubuh yang dilindas, yang ditindas?