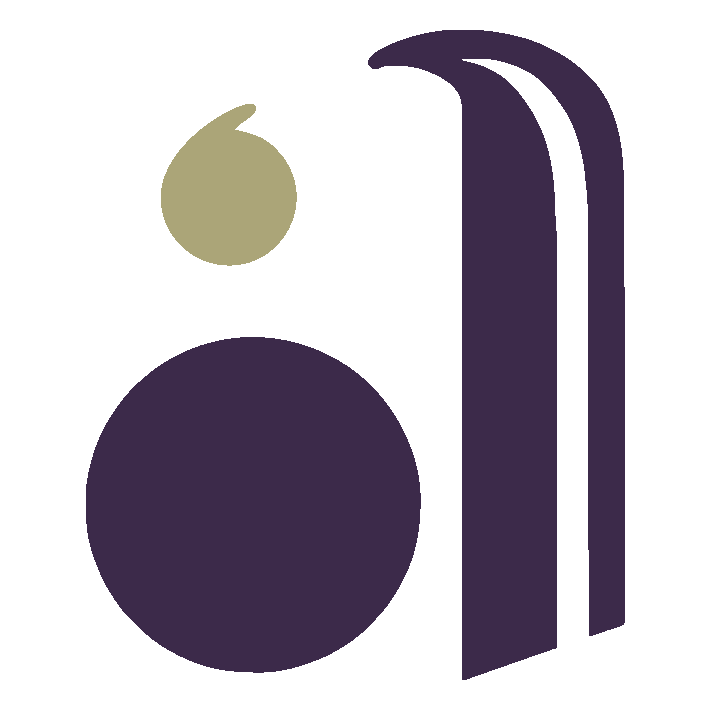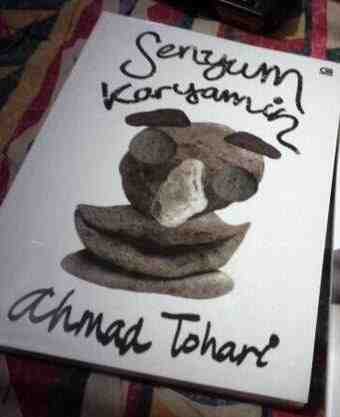Ada sesuatu yang selalu menekan tatkala seseorang menuliskan tentang kamp. Tekanan itu bukan sekadar soal sejarah yang penuh darah, tetapi lebih pada rasa bersalah karena menyentuh luka yang tak pernah benar-benar pulih. Bagaimana menuliskan penderitaan tanpa mengubahnya menjadi pameran? Bagaimana menyusun kata-kata agar tidak berubah menjadi museum bisu yang meringankan beban pembaca tetapi mengkhianati beban mereka yang pernah hidup di dalam pagar kawat?
Karya Rudolf Mrázek, The Complete Lives of Camp People: Colonialism, Fascism, Concentrated Modernity (2020), sejak awal memaksa kita untuk bergulat dengan dilema itu. Ia tidak memilih jalan besar tentang pertempuran, deklarasi, atau kepahlawanan.
Ia menurunkan kameranya ke hal-hal yang tampak tetek bengek: sepotong baju, sebuah sendok, fragmen musik Chopin, bahkan desau radio di tengah hutan Papua. Dalam potongan-potongan kecil itu, kita mendapati sebuah arsip liyan dari modernitas, yaitu arsip yang lahir bukan dari buku teks, melainkan dari tubuh-tubuh yang dikurung, dari napas yang terputus, dari pakaian yang semakin aus dipakai hari demi hari.
Modernitas, dalam tafsir Mrázek, bukan hanya mesin dan ide besar. Ia adalah sesuatu yang terkonsentrasi, dipadatkan dalam ruang sempit kamp, hingga hal paling banal sekalipun bisa menjadi persoalan hidup dan mati. Ia menulis bahwa di Boven Digoel dan Theresienstadt, bahkan bagaimana seseorang memegang sendok, atau memainkan sebuah étude Chopin dapat menentukan ritme hidup dan derajat keberadaannya.
Menulis tentang kamp, kata Mrázek, hanya sah jika dilakukan dalam keadaan “takut hingga tulisan itu sendiri seperti dipaksa hadir oleh ketakutan” (Mrázek, 2020, hlm. 4). Di titik inilah kita, sebagai pembaca, dipaksa untuk berhenti sejenak: barangkali bukan kebenaran yang dicari, melainkan kesaksian yang genting, rapuh, dan selalu terancam hilang.
Kamp sebagai Arsip Modernitas yang Retak
Dua kamp yang menjadi poros buku ini lahir dari dua dunia yang tampak berbeda. Theresienstadt, sebuah kota rococo kecil di Cekoslowakia yang berubah menjadi “ghetto” Nazi pada 1942, adalah simbol peradaban Eropa yang dipermak menjadi etalase tipuan.
Boven Digoel, sebuah clearing di hutan belantara Papua, didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1927 untuk menyingkirkan para pemberontak politik dari Jawa dan Sumatra. Satu dilingkupi tembok barok, yang liyan berdiri di ujung dunia, “satu langkah lagi dan engkau akan jatuh ke luar bumi” kata para tahanan (Mrázek, 2020, hlm. 3).
Namun di balik jarak geografis dan perbedaan ideologis itu, keduanya memperlihatkan gejala yang sama: modernitas yang dihancurkan sekaligus dibentuk kembali. Orang-orang yang dibuang ke kedua kamp ini bukanlah mereka yang buta huruf atau asing dari zaman. Sebaliknya, mereka adalah bagian dari masyarakat yang berpendidikan, kosmopolitan, dan sering kali lebih “modern” dibanding lingkungan yang menyingkirkan mereka. Justru karena “terlalu modern,” mereka dianggap berbahaya dan harus disingkirkan.
Mrázek menolak membandingkan keduanya secara simplistis. Ia menyebut bahwa “kecuali untuk ‘kecamp-an’ mereka, keduanya hampir tak memiliki kesamaan”. Tetapi justru dalam serpihan-serpihan modernitas yang terpecah, keduanya membentuk konstelasi yang sama: sebuah peringatan tentang betapa rapuhnya gagasan kemajuan.
Dalam kedua kamp itu, hal-hal remeh yang biasanya hanya latar kiwari berdiri di tengah panggung. Sebuah mantel, cara seseorang menaruh topi, bahkan setangkai pena yang diselipkan di saku bisa menjadi tanda kehidupan. Mrázek menyebutnya sebagai trivial-sublime, sesuatu yang remeh berubah menjadi menggetarkan (Mrázek, 2020, hlm. 4). Di dalam ruang yang begitu sempit, trivialitas justru menjadi medium terakhir untuk mempertahankan martabat manusia.
Tubuh, Pakaian, dan Mode di Tengah Kekuasaan
Pakaian, dalam kehidupan sehari-hari, sering dianggap sebagai lapisan tipis yang menutupi tubuh. Namun, di dalam kamp, pakaian menjelma menjadi penanda eksistensi, sebuah bahasa sunyi tentang martabat, status, bahkan nasib.
Di Theresienstadt, para perempuan tua melangkah dengan topi berhiaskan bulu untaian yang terkulai, payung renda yang dulu hanya dipakai pada pesta, kini dipakai untuk menghalau lalat. Seorang bocah berusia empat belas tahun, Petr Ginz, menuliskan dalam catatannya bagaimana ia berangkat dengan tiga pasang kaus kaki, dua kemeja, dan sebuah mantel musim dingin, seolah berpakaian berlapis adalah perisai terakhir menghadapi ketidakpastian (Mrázek, 2020, hlm. 13).
Sementara itu di Boven Digoel, para tahanan politik dari Jawa dan Sumatra menampilkan paradoks yang tidak kalah mencolok. Ketika turun dari kapal setelah perjalanan panjang ke pedalaman Papua, banyak di antara mereka yang “berpakaian rapi ala Eropa, dengan jas putih, sepatu kulit, dan payung terselip di ketiak” (Mrázek, 2020, hlm. 14). Seorang dokter Belanda mencatat dengan nada getir bahwa mereka bahkan mengenakan kaus kaki dengan motif garis mencolok, pena di saku, dan sepatu berlinang, seolah mereka bukan pemberontak buangan, melainkan pegawai kota besar yang siap masuk kantor.
Mereka menolak dilucuti dari martabatnya dengan berpakaian rapi. Mode, dalam situasi demikian, menjadi bentuk diam dari penolakan. Soetan Sjahrir menulis dari kamp kepada istrinya, meminta dikirimkan piyama dan celana dalam karena yang dimilikinya telah usang, “terlalu kasar” untuk dipakai sehari-hari (Mrázek, 2020, hlm. 17). Permintaan kecil itu adalah jeritan untuk tetap hidup sebagai manusia.
Mrázek menahbis fenomena ini sebagai trivial-sublime, banalitas yang berubah menjadi sublime. Dalam kondisi ekstrem, pakaian tidak lagi sekadar pelindung tubuh, tetapi perisai eksistensial. “Mode,” tulisnya, “di kamp menjadi benar-benar mematikan; ironi paling kejam sekaligus daya tarik paling manusiawi” (Mrázek, 2020, hlm. 23).
Suara, Musik, Radio
Jika pakaian adalah bahasa diam, maka suara adalah denyut kehidupan. Di Theresienstadt, musik klasik tetap dimainkan di bawah bayangan Auschwitz. Orkestra kamp memainkan Beethoven atau Dvořák, bahkan ketika para pemainnya tahu bahwa besok atau lusa mereka mungkin sudah berada di gerbong menuju kematian.
Seorang bocah bernama Pavel Weiner menulis dalam buku hariannya tentang antrean panjang di udara dingin untuk mendapatkan sarung tangan, sambil mendengar musik samar dari barak liyan. Kehidupan sehari-hari kamp diatur oleh ritme kebisingan—noise—yang memaksa tubuh tunduk.
Boven Digoel menghadirkan lanskap bunyi yang berbeda, tetapi tak kalah sarat makna. Di tengah hutan Papua, para tahanan mendengar suara azan dari masjid kecil, bercampur dengan dentuman hujan tropis dan lengking serangga malam. Kadang, sebuah radio membawa siaran dari Batavia atau Surabaya, menghadirkan dunia luar yang terasa sekaligus dekat dan mustahil dijangkau (Mrázek, 2020, hlm. 119).
Musik di Theresienstadt, dimainkan dengan keterampilan, justru terdengar seperti ironi: harmoni indah yang menutupi kekacauan tak terbayangkan. Sementara di Boven Digoel, suara alam liar berpadu dengan suara manusia buangan, menciptakan orkestra ganjil antara modernitas dan rimba. Kedua lanskap suara ini menghadirkan harmoni yang patah—melodi yang terus dimainkan, tetapi retak di setiap nadanya.
Modernitas yang Dipadatkan
Kamp juga menciptakan lanskap anyar: kota-kota semu yang berdiri di atas reruntuhan kebebasan. Theresienstadt dipoles ulang oleh Nazi menjadi Potemkin village. Jalan-jalan diperindah, toko pakaian dibuka, bahkan papan nama Herrenbekleidung terpampang di etalase (Mrázek, 2020, hlm. 16).
Cahaya memainkan peran besar dalam ilusi itu. Tahun 1944, delegasi Palang Merah Internasional datang dan mencatat bahwa “orang-orang di jalan berpakaian rapi, perempuan terlihat anggun dengan tas dan stoking sutra, bahkan ada anak muda dengan gaya zazou” (Mrázek, 2020, hlm. 22). Apa yang mereka lihat bukanlah kenyataan, melainkan panggung.
Boven Digoel menawarkan kontras lain. Tidak ada lampu-lampu kota atau etalase toko; hanya clearing di tengah hutan. Namun, di sana juga lahir “kota”: blok-blok kayu, jalan tanah, pasar kecil tempat pakaian peninggalan orang mati dijual (Mrázek, 2020, hlm. 19). Cahaya yang ada hanyalah sinar mentari tropis dan pelita minyak. Keduanya memperlihatkan wajah modernitas yang dipadatkan. Kota kamp adalah eksperimen sosial di mana tata ruang, cahaya, dan aturan diatur ulang untuk mengendalikan manusia, baik dalam panggung propaganda Nazi maupun laboratorium kolonial Belanda.
Mual, Pelarian, dan Debu Ingatan
Pada akhirnya, kamp meninggalkan rasa mual, keinginan melarikan diri, dan debu kenangan.
Mual itu bukan hanya akibat penyakit, melainkan kondisi eksistensial berupa rasa muak terhadap dunia yang menyempit menjadi pagar, terhadap udara yang selalu sama, terhadap waktu yang beku.
Beberapa orang mencoba melarikan diri. Di Boven Digoel, Thomas Najoan mencoba kabur tiga kali; dua kali ia dikembalikan, pada percobaan ketiga ia lenyap ke dalam hutan, hanya kabar mayatnya yang ditemukan di sungai (Mrázek, 2020, hlm. 20). Upaya pelarian bukan sekadar mencari kebebasan, tetapi juga bentuk penolakan terakhir terhadap absurditas.
Yang tertinggal hanyalah debu. Ingatan para penyintas sering rapuh, penuh kabut, tetapi justru dalam kerentanannya ingatan itu tumbuh muda kembali—aging in reverse, “penuaan terbalik”. Debu bukan akhir, melainkan residu sejarah yang melekat di pakaian, surat, foto-foto. Seperti ditulis Adorno, “pembunuhan tidak terjadi sekali waktu; ia terjadi terus-menerus, dalam bentuk yang sama yang berulang tanpa akhir” (Mrázek, 2020).
Arkian, menulis tentang kamp selalu berarti berjalan di ambang luka. Kata-kata tidak pernah cukup, bahkan cenderung patah pucuk, namun justru dalam kegagalannya terdapat kejujuran. Mrázek menyebut menulis tentang kamp hanya mungkin sebagai analisis pelarian, napas yang tersengal, pandangan yang selalu menoleh ke belakang.
Boven Digoel dan Theresienstadt, meski berbeda, memperlihatkan hal ihwal yang sama: bahwa modernitas bukanlah kisah mulus tentang kemajuan, melainkan serpihan-serpihan yang retak, terkonsentrasi, dan sering kali mematikan. Pakaian, suara, cahaya, dan bahkan debu—semuanya adalah bagian dari sejarah yang lebih luas, sejarah tentang bagaimana manusia mencoba bertahan ketika dunia runtuh di sekelilingnya.
Hari ini, kita hidup jauh dari kamp, tetapi jejaknya masih bersama kita. Di pinggiran kota yang tumbuh seperti suburb tanpa jiwa, di ruang digital yang mengurung kita dalam algoritma, dalam birokrasi yang mengatur tubuh kita dengan cara halus. Fragmen kamp itu masih hadir. Kita mungkin tidak menyebutnya kamp, tetapi logikanya tetap menghantui.
Mungkin, seperti ditulis Walter Benjamin tentang mode, sejarah adalah upaya mengejek kematian. Walakin di balik ejekan itu, kita selalu diingatkan: tidak ada modernitas yang bebas dari bayang-bayang kamp.