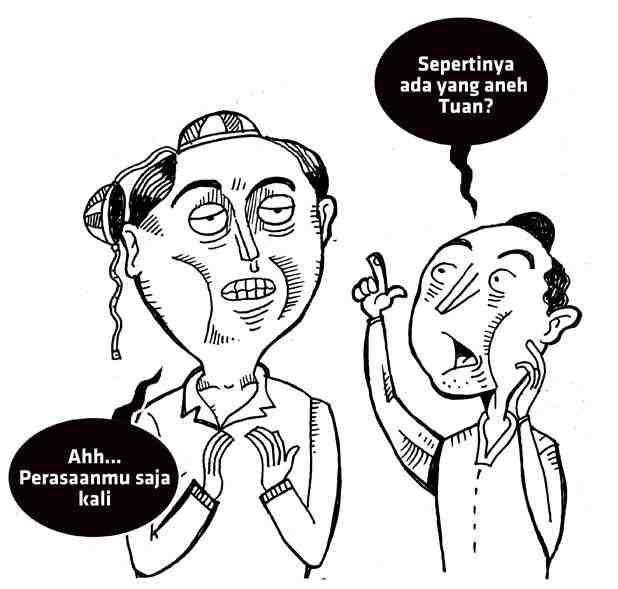Al-Hamadhani, Sufi yang Mati Dua Kali
Tubuh bisa hancur, tetapi kata tidak. Hukum bisa berubah, tetapi kebenaran batin selalu mencari bentuk baru untuk hidup.

Hamadhani adalah kota yang seolah bernafas dalam dua zaman sekaligus. Di lembah antara Khurasan dan Baghdad itu, udara dingin membawa jejak pena Ibnu Sina, sang tabib dan filsuf yang wafat di sana, meninggalkan aroma tinta yang tak pernah benar-benar hilang.
Dua abad setelahnya, di jalan berbatu yang sama, lahir seorang anak dari keluarga hakim. Ia kelak masyhur sebagai Ainul Quat Al-Hamadhani, nama yang berarti “mata para hakim”. Sebuah julukan yang terdengar seperti takdir, tetapi akhirnya berubah menjadi ironi, sebab ia justru akan digantung oleh para hakim sezamannya.
Kota yang pernah menjadi rumah bagi para filsuf dan penyair itu juga menjadi panggung bagi kematian seorang sufi muda yang menulis tentang cinta dan kematian sebagai jalan menuju Tuhan. Hamadhani memeluk dua wajah: rumah pengetahuan dan tiang gantungan. Di antara suara azan dan derap kuda para penakluk, kota itu menyimpan bisikan yang datang dari dunia lain. Di sanalah seorang pemuda menulis bahwa mati bukanlah akhir, melainkan jalan rahasia menuju cahaya yang tak dapat dijelaskan oleh akal. Ia menulis dengan keyakinan yang melampaui kehidupan itu sendiri, dan karenanya ia harus mati untuk membuktikannya.
Menurut Firoozeh Papan-Matin dalam Beyond Death: The Mystical Teachings
of ʿAyn al-Quāt al-Hamadhānī (Brill, 2010), Al-Hamadhani lahir sekira titimangsa 1096 dari keluarga para hakim bergelar Syafi’i. Kakek dan ayahnya adalah qadi, sosok yang dihormati karena pengetahuan dan kewenangan mereka dalam hukum Islam. Dari garis inilah nama kehormatannya muncul. Tetapi di balik silsilah terhormat itu, mengalir darah yang juga haus akan makna batin. Ayahnya, Abu Bakr Muḥammad, bukan hanya ahli fikih, melainkan juga pengembara spiritual. Dalam catatan Tamhidat, sang anak mengenang malam ketika mereka menari di rumah seorang sufi dan tiba-tiba sang ayah berkata ia melihat Ahmad Ghazali menari bersama mereka. Bukan dalam mimpi, melainkan dalam kesadaran yang lain. Saat itu, batas antara dunia nyata dan gaib seolah terbelah.
Kakeknya pun meninggal dengan cara yang tak wajar. Catatan sejarah menyebutnya syahid, meskipun kata itu tidak selalu berarti gugur karena iman, bisa juga karena kekacauan. Sejak awal, keluarga itu hidup di antara kemuliaan dan tragedi, di antara hukum dan penglihatan batin. Dari rahim semacam inilah lahir seorang anak yang akan menulis tentang kematian dengan tinta yang bercampur darahnya sendiri. Ia mewarisi dua mata: satu untuk hukum, satu lagi untuk rahasia Tuhan.
Di usia muda, kecerdasannya sudah menarik perhatian. Ia masuk ke lingkaran para pemikir besar abad ke-12, masa ketika peradaban Islam tengah mencari keseimbangan baru antara ortodoksi dan kebebasan berpikir. Namun yang paling menentukan hidupnya adalah pertemuan dengan Ahmad Ghazali, adik dari sang hujjatul Islam, Abu Hamid al-Ghazali. Jika sang kakak menegakkan tembok ortodoksi, maka sang adik membukakan pintu cinta mistik. Dari Ahmad, Al-Hamadhani belajar bahwa cinta kepada Tuhan sering kali bertentangan dengan hukum manusia, dan bahwa Iblis pun bisa menjadi pecinta sejati karena menolak bersujud kepada Adam demi menjaga keesaan cintanya kepada Sang Pencipta.
Ia menyerap api dari Ahmad Ghazali dan menyulamnya dengan filsafat Ibnu Sina. Ia membaca bahwa akal hanyalah perahu di permukaan, sedangkan pengetahuan sejati hanya didapat dengan menyelam ke kedalaman samudra jiwa. Dari sanalah lahir pandangan yang memadukan rasionalitas dan ekstase, logika dan paradoks. Ia bukan hanya murid Ghazali, tetapi juga sahabat para filsuf yang percaya bahwa kebenaran tak bisa dibatasi oleh hukum atau tradisi. Di tengah dunia yang kian kaku oleh doktrin, ia menulis dengan suara yang mengalir seperti air, kadang jernih, kadang menipu kedalaman.
Namun dunia tidak memberi tempat bagi orang yang menulis di atas garis api. Ia hidup di masa ketika setiap kata bisa disalahartikan sebagai penghinaan terhadap hukum Tuhan. Tapi justru di bawah bayangan itu ia menulis paling keras. Bagi Al-Hamadhani, menulis adalah cara bertahan di tepi jurang, di antara langit dan neraka. Setiap kalimat adalah taruhan, setiap kata bisa menjadi tali gantung bagi tubuhnya. Ia tahu risikonya, tetapi terus menulis.
Karya-karyanya yang bertahan hingga kini menjadi semacam peta perjalanan spiritual. Dalam Tamhidat, ia menyebut kematian sebagai pintu menuju pengetahuan gaib. “Barangsiapa belum mati sebelum mati,” tulisnya, “ia belum mengenal rahasia kehidupan.” Zubdatul Ḥaqāʾiq memperdalam pandangannya tentang realitas dan lapisan-lapisan cahaya yang harus ditembus manusia untuk sampai kepada Tuhan. Sedangkan Maktubaat, kumpulan surat pribadinya, menyingkap sisi manusiawi seorang sufi muda yang tahu bahwa hidupnya sedang dihitung mundur. Surat-surat itu mengalir lembut dan getir, seperti doa yang ditulis di atas pasir sebelum ombak datang.
Namun yang paling menyayat adalah Shakwā al-Gharīb, “Keluhan Seorang Asing,” yang ia tulis di penjara Baghdad. Di dalamnya ia membela diri bukan hanya dari tuduhan sesat, tetapi juga dari rasa sepi yang melingkupi dirinya. Ia berwicara seperti Socrates yang menanti racun, dengan keyakinan bahwa kebenaran tidak butuh pembelaan, hanya kesetiaan. Papan-Matin menyebut buku ini sebagai “dokumen eksistensial,” sebuah percakapan antara tubuh yang terpenjara dan jiwa yang sudah merdeka.
Dalam kesunyian penjara, ia menulis dengan pena yang seolah diukir dari tulangnya sendiri. Setiap kalimat menjadi ruang doa, setiap metafora adalah jeritan halus yang ditujukan kepada Tuhan. Ia tahu, dunia luar sedang menunggu eksekusinya. Tetapi menulis, baginya, adalah cara untuk mati dengan sadar. Ia tidak berusaha melawan hukuman, hanya ingin memastikan bahwa kematiannya memiliki makna.
Sejak muda, ia percaya bahwa kematian sejati bukanlah kematian tubuh, melainkan kematian ego. Ia menyebutnya mauti ma’nawi, mati maknawi, mati sebelum mati. Dalam pengalaman mistis itu, seseorang tidak lagi melihat dengan matanya sendiri, melainkan dengan cahaya Tuhan. Ia menulis bahwa orang yang telah mati secara batin akan hidup dalam penglihatan yang tak bisa dijangkau oleh logika. Namun pada akhirnya, ajaran yang terlalu tinggi untuk dipahami banyak orang itu justru menjadi dasar bagi tuduhan bahwa ia sesat.
Titimangsa 1131, para ulama ortodoks menuduhnya mengagungkan Iblis, meremehkan syariat, dan mengajarkan bahwa hukum hanyalah kulit luar dari kebenaran. Tuduhan itu cukup untuk menyeretnya ke tiang gantungan. Ia dibawa ke pasar Hamadhan, di hadapan orang banyak, lalu dijatuhi hukuman mati. Ironinya, ia yang menulis tentang mati sebelum mati justru dipaksa mati di depan mata dunia.
Tubuhnya tergantung, tetapi kata-katanya tidak ikut mati. Seperti halnya al-Hallaj seabad sebelumnya, ia meninggalkan lebih banyak kehidupan dalam kematiannya. Ia tidak hanya mati sekali, tetapi dua kali: pertama dalam dunia batin, kedua di hadapan publik. Kematian pertama membuka jalan menuju cahaya gaib, kematian kedua membuka jalan menuju sejarah. Antara keduanya, ia menjadi legenda yang hidup lebih panjang dari umur tubuhnya sendiri.
Setelah eksekusi itu, ajarannya tidak lenyap. Justru dari reruntuhan reputasi dan darah di tanah Hamadhan, suaranya menyeberangi benua. Di India, melalui tarekat Chishti, karya-karyanya menemukan kehidupan baru. Sufi besar Khawaja Banda Nawaz Gisudaraz menulis tafsir panjang atas Tamhadat dan memperlakukan Al-Hamadhani seperti seorang penafsir rahasia kosmos. Ia melarang murid-murid pemula membaca karya itu karena terlalu dalam, terlalu berbahaya bagi jiwa yang belum matang. Namun di tangan para murid lanjut, teks itu dibaca dengan hati bergetar, diiringi musik dan zikir yang menjadi bagian dari perjalanan spiritual mereka.
Dalam majelis zikir Chishti, musik menjadi jembatan antara tubuh dan jiwa. Denting rebana dan lantunan qawwalimengguncang hati hingga batas kesadaran terbelah.
Bagi para sufi, musik adalah kematian kecil, fanaʾ sementara yang membawa jiwa keluar dari belenggu dunia. Pandangan itu berasal dari Al-Hamadhani, yang melihat musik bukan sebagai hiburan, tetapi sebagai cermin: jika hati kotor, musik akan menyalakan nafsu; tetapi jika hati bersih, ia akan menyalakan cinta. Ia menulis bahwa ketika musik membuatmu lupa dunia, itu adalah zikir; tetapi ketika ia menjeratmu pada dunia, itu adalah syahwat.
Di sini, ajarannya menemukan rumah yang lebih damai. Jauh dari pengawasan ortodoksi Saljuq, kata-katanya menjadi bagian dari nyanyian spiritual yang terus berkumandang di India dan Pakistan hingga kiwari. Ia mungkin digantung di Hamadhani, tetapi suaranya hidup dalam lagu yang dinyanyikan dengan mata terpejam dan dada terbuka. Dalam setiap irama yang memanggil nama Tuhan, ada gema dari seorang sufi yang mati dua kali.
Al-Hamadhani tidak pernah bermaksud mendirikan sekte atau menantang penguasa. Ia hanya menulis tentang cinta yang menembus batas akal, cinta yang menolak dikurung dalam hukum. Namun dunia jarang memaafkan keberanian yang tidak sejalan dengan aturan. Ia dibungkam dengan tali, tetapi kata-katanya tetap berjalan, melintasi bahasa, budaya, dan zaman. Dari Persia ke India, dari Baghdad ke Delhi, suaranya berpindah-pindah seperti cahaya yang menolak padam.
Kini, delapan abad kemudian, membaca tulisannya seperti mendengar gema yang datang dari masa lalu. Suaranya tidak lagi milik dunia Islam saja, melainkan milik semua yang pernah percaya bahwa kebenaran lebih besar dari rasa takut. Ia mengajarkan bahwa setiap manusia harus mati dua kali: sekali untuk meninggalkan dunia, dan sekali untuk meninggalkan dirinya sendiri. Hanya dengan begitu kita bisa hidup selamanya di dalam makna.
Mungkin inilah yang dimaksudnya dengan hidup setelah mati. Ia tidak berbicara tentang surga dan neraka, melainkan tentang kesadaran yang melampaui tubuh. Tentang keberanian untuk menatap kematian tanpa gentar, karena tahu bahwa kematian bukan akhir, melainkan gerbang. Ia mengajarkan bahwa tiang gantungan bisa menjadi mihrab, tempat pertemuan terakhir antara jiwa dan Tuhan.
Ironinya, para penguasa yang mengira telah menghapus namanya justru menjadikannya abadi. Tiang gantungan yang seharusnya membungkam suaranya malah menjadi menara yang memantulkan gema ke segala arah. Seperti api kecil yang menyalakan obor, kata-katanya menyebar ke hati para murid yang meneruskan zikir dan musiknya. Mereka menyebutnya bukan sebagai pemberontak, tetapi sebagai saksi bahwa pengetahuan sejati lahir dari luka.
Mungkin itulah pelajaran terbesar dari kisah ini: bahwa tubuh bisa hancur, tetapi kata tidak. Hukum bisa berubah, tetapi kebenaran batin selalu mencari bentuk baru untuk hidup. Seperti musik yang terus berputar dalam majelis zikir, kata-kata Al-Hamadhani terus berputar di hati manusia. Kadang lirih, kadang nyaring, tetapi tak pernah benar-benar hilang.
Arkian, Kota Hamadhani masih berdiri. Udara dinginnya masih menyimpan bisikan yang sama. Mungkin jika kita berjalan di jalan berbatu tempat ia digantung, kita masih bisa mendengar gema samar suara seorang sufi muda yang berbicara kepada waktu.
Ia berkata dengan nada nan lampas dan penuh ironi: kematian bukanlah kehancuran, melainkan bentuk tertinggi dari pengetahuan. Ia mati dua kali, tapi justru karena itu, ia hidup selamanya.