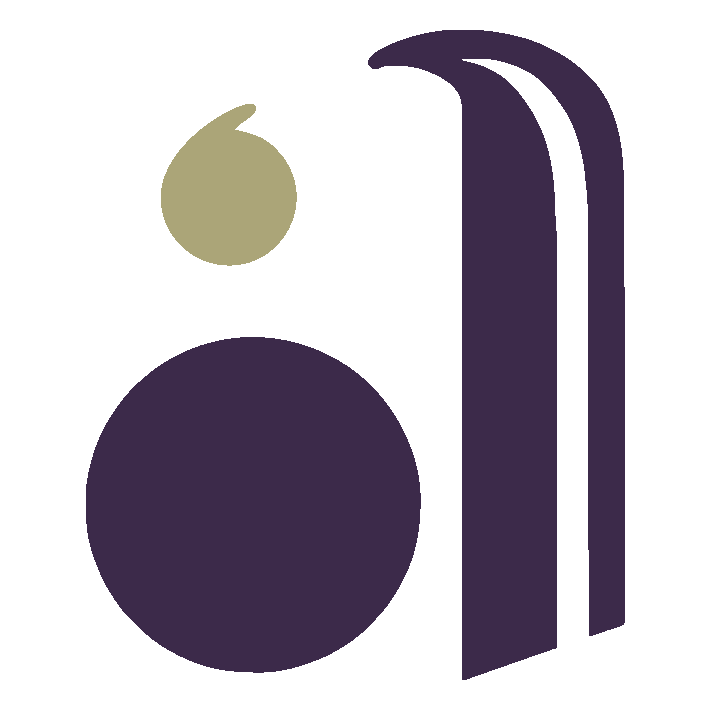Tarikh
|
Sejarah Indonesia
Mengingat Onghokham: Jaringan Islam/Pesantren di Madiun Abad ke-19
Muhammad Iqbal
Minggu, 31 Agustus 2025 | 12:39 WIB
Bagaimana Onghokham, seorang sejarawan Tionghoa menulis Islam dan pesantren di Madiun abad 19 atau era kolonial?

Kabut tipis masih menggantung tatkala pagi di Madiun abad ke-19 dibuka oleh dua bunyi yang berasal dari dunia berbeda. Dari pusat kota, dentang lonceng gereja Belanda menggema, tanda berjalannya jam administrasi kolonial.
Dari arah sawah, azan subuh mengalun lirih, mengisi udara dengan gema yang telah lama dikenal petani. Kedua suara itu bertemu, berlapis dalam udara lembab pedesaan, melukiskan benturan dua tatanan: kekuasaan dari luar dengan perangkat pajak dan militernya, serta iman yang tumbuh dari tanah, menyatu dengan air, lumpur, dan padi.
Islam di Madiun abad ke-19 bukanlah institusi yang menggelegar di ruang publik dengan deklarasi politik atau perang besar. Ia hadir sebagai denyut halus, sebagai kerangka makna yang mengatur ritme kehidupan sehari-hari. Clifford Geertz (1973) menyebut agama sebagai “a system of symbols”, peta makna yang menuntun manusia menafsirkan dunia. Bagi petani Madiun, Islam menjadi bahasa yang menjelaskan hubungan mereka dengan tanah, dengan sesama, dan dengan kekuasaan asing yang menekan dari atas.
Onghokham dalam buku Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priayi dan Petani di Keresidenan Madiun Abad XIX (2018) menegaskan, berbeda dengan kota bangsawan Jawa seperti Surakarta atau Yogyakarta, Madiun pada abad ke-19 adalah “frontier”, ruang perbatasan nan cair, dibuka dan ditata oleh Belanda sesuai kepentingan kolonial (hlm. 45). Akan tetapi dalam ruang cair itu, desa-desa tetap berdenyut. Masjid kecil di tepi sawah, kiai desa yang memberi ceramah tentang kejujuran dan sabar, serta tradisi slametan yang diberi bingkai doa Islam. Semuanya menyusun jalinan makna yang membuat masyarakat bertahan.
Desa sebagai Denyut Kehidupan
Bagi orang Madiun abad ke-19, desa bukan sekadar alamat, melainkan dunia itu sendiri. Di situlah sawah, langgar, dan pasar membentuk lingkaran kehidupan yang terus berulang. Residen Belanda di kota mungkin mengatur administrasi, tetapi denyut utama tetap terletak di desa, di ruang solidaritas dan musyawarah.
Belanda menata ulang struktur desa dengan melibatkan lurah dan carik sebagai perpanjangan tangan negara. Lurah menjadi penghubung antara instruksi kolonial dan masyarakat tani; carik mencatat pajak, mengawasi setoran, dan memastikan kerja rodi terkumpul (Ong, 2018, hlm. 47-48). Namun di balik struktur administratif itu, ada lapisan liyan yang lebih menentukan: jaringan Islam yang mengalir lewat masjid, langgar, dan pondok pesantren kecil.
Masyarakat Muslim di masjid tidak hanya salat berjamaah. Mereka bermusyawarah, menentukan giliran air irigasi, atau menyelesaikan sengketa tanah. Di langgar bambu berlantai tanah, anak-anak belajar mengaji, petani singgah sebentar setelah mencangkul. Islam, tulis Ong (2018), “hidup dalam etika petani, dalam kebiasaan sehari-hari, lebih daripada dalam upacara besar” (hlm. 53).
Kiai desa bukan tokoh politik besar, melainkan penjaga moral. Ia memastikan masyarakat tidak tercerai-berai oleh tekanan pajak dan kerja rodi. Kehadirannya menjadi perekat sosial, mengingatkan bahwa sabar bukan pasrah, melainkan cara menjaga martabat di bawah kolonialisme Dengan demikian, desa-desa di Madiun memperlihatkan wajah ganda: secara administratif terikat pada Belanda, tetapi secara kultural berakar pada Islam. Langgar menjadi kawah candradimuka masyarakat menenun solidaritas di sela tekanan kolonial.
Priayi, Kejawen, dan Ambivalensi Islam
Namun, desa bukan satu-satunya wajah Madiun. Ada pula priayi, yaitu lapisan birokrasi Jawa yang menjadi perantara kolonial. Mereka adalah pejabat desa, lurah, carik, hingga bupati yang menjembatani dua dunia. Tetapi posisi ini penuh ambivalensi. Priayi, menurut Ong (2018), menggabungkan loyalitas pada Belanda dengan simbol-simbol Islam yang tetap hidup di masyarakat (hlm. 63). Mereka hadir di masjid, mendukung acara keagamaan, bahkan membangun langgar. Walakin kesalehan itu sering kali berfungsi sebagai legitimasi politik, cara untuk mengurangi jarak dengan rakyat.
Orientasi kultural priayi sebenarnya condong pada kejawen, yakni tradisi keraton, mistik Jawa, dan praktik sinkretis. Slametan, konsultasi pada dukun, atau pembacaan kitab Jawa tetap dijalankan. Clifford Geertz (1973) menyebut ketegangan ini dalam dikotomi “santri” dan “abangan”. Priayi Madiun lebih dekat ke abangan, meski Ong (2018) mengingatkan bahwa kategori itu cair dan tumpang tindih (hlm. 66).
Di satu sisi, priyayi menjadi perpanjangan kekuasaan kolonial yang memungut pajak. Di sisi lain, mereka butuh legitimasi Islam agar tidak sepenuhnya dipandang asing. Ambivalensi ini sering menimbulkan jarak dengan kiai. Jika kiai menekankan moral dan kesederhanaan, priayi dipandang sebagai penyambung beban kolonial. Tetapi dalam ruang abu-abu itu, kadang justru muncul perlindungan: lurah yang “menutup mata” atas setoran pajak yang kurang, atau carik yang melaporkan jumlah tenaga kerja lebih rendah demi warganya (Ong, 2018, hlm. 74).
Islam di Madiun abad ke-19 bukanlah institusi yang menggelegar di ruang publik dengan deklarasi politik atau perang besar. Ia hadir sebagai denyut halus, sebagai kerangka makna yang mengatur ritme kehidupan sehari-hari. Clifford Geertz (1973) menyebut agama sebagai “a system of symbols”, peta makna yang menuntun manusia menafsirkan dunia. Bagi petani Madiun, Islam menjadi bahasa yang menjelaskan hubungan mereka dengan tanah, dengan sesama, dan dengan kekuasaan asing yang menekan dari atas.
Onghokham dalam buku Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priayi dan Petani di Keresidenan Madiun Abad XIX (2018) menegaskan, berbeda dengan kota bangsawan Jawa seperti Surakarta atau Yogyakarta, Madiun pada abad ke-19 adalah “frontier”, ruang perbatasan nan cair, dibuka dan ditata oleh Belanda sesuai kepentingan kolonial (hlm. 45). Akan tetapi dalam ruang cair itu, desa-desa tetap berdenyut. Masjid kecil di tepi sawah, kiai desa yang memberi ceramah tentang kejujuran dan sabar, serta tradisi slametan yang diberi bingkai doa Islam. Semuanya menyusun jalinan makna yang membuat masyarakat bertahan.
Desa sebagai Denyut Kehidupan
Bagi orang Madiun abad ke-19, desa bukan sekadar alamat, melainkan dunia itu sendiri. Di situlah sawah, langgar, dan pasar membentuk lingkaran kehidupan yang terus berulang. Residen Belanda di kota mungkin mengatur administrasi, tetapi denyut utama tetap terletak di desa, di ruang solidaritas dan musyawarah.
Belanda menata ulang struktur desa dengan melibatkan lurah dan carik sebagai perpanjangan tangan negara. Lurah menjadi penghubung antara instruksi kolonial dan masyarakat tani; carik mencatat pajak, mengawasi setoran, dan memastikan kerja rodi terkumpul (Ong, 2018, hlm. 47-48). Namun di balik struktur administratif itu, ada lapisan liyan yang lebih menentukan: jaringan Islam yang mengalir lewat masjid, langgar, dan pondok pesantren kecil.
Masyarakat Muslim di masjid tidak hanya salat berjamaah. Mereka bermusyawarah, menentukan giliran air irigasi, atau menyelesaikan sengketa tanah. Di langgar bambu berlantai tanah, anak-anak belajar mengaji, petani singgah sebentar setelah mencangkul. Islam, tulis Ong (2018), “hidup dalam etika petani, dalam kebiasaan sehari-hari, lebih daripada dalam upacara besar” (hlm. 53).
Kiai desa bukan tokoh politik besar, melainkan penjaga moral. Ia memastikan masyarakat tidak tercerai-berai oleh tekanan pajak dan kerja rodi. Kehadirannya menjadi perekat sosial, mengingatkan bahwa sabar bukan pasrah, melainkan cara menjaga martabat di bawah kolonialisme Dengan demikian, desa-desa di Madiun memperlihatkan wajah ganda: secara administratif terikat pada Belanda, tetapi secara kultural berakar pada Islam. Langgar menjadi kawah candradimuka masyarakat menenun solidaritas di sela tekanan kolonial.
Priayi, Kejawen, dan Ambivalensi Islam
Namun, desa bukan satu-satunya wajah Madiun. Ada pula priayi, yaitu lapisan birokrasi Jawa yang menjadi perantara kolonial. Mereka adalah pejabat desa, lurah, carik, hingga bupati yang menjembatani dua dunia. Tetapi posisi ini penuh ambivalensi. Priayi, menurut Ong (2018), menggabungkan loyalitas pada Belanda dengan simbol-simbol Islam yang tetap hidup di masyarakat (hlm. 63). Mereka hadir di masjid, mendukung acara keagamaan, bahkan membangun langgar. Walakin kesalehan itu sering kali berfungsi sebagai legitimasi politik, cara untuk mengurangi jarak dengan rakyat.
Orientasi kultural priayi sebenarnya condong pada kejawen, yakni tradisi keraton, mistik Jawa, dan praktik sinkretis. Slametan, konsultasi pada dukun, atau pembacaan kitab Jawa tetap dijalankan. Clifford Geertz (1973) menyebut ketegangan ini dalam dikotomi “santri” dan “abangan”. Priayi Madiun lebih dekat ke abangan, meski Ong (2018) mengingatkan bahwa kategori itu cair dan tumpang tindih (hlm. 66).
Di satu sisi, priyayi menjadi perpanjangan kekuasaan kolonial yang memungut pajak. Di sisi lain, mereka butuh legitimasi Islam agar tidak sepenuhnya dipandang asing. Ambivalensi ini sering menimbulkan jarak dengan kiai. Jika kiai menekankan moral dan kesederhanaan, priayi dipandang sebagai penyambung beban kolonial. Tetapi dalam ruang abu-abu itu, kadang justru muncul perlindungan: lurah yang “menutup mata” atas setoran pajak yang kurang, atau carik yang melaporkan jumlah tenaga kerja lebih rendah demi warganya (Ong, 2018, hlm. 74).
Ambivalensi priayi memperlihatkan bahwa Islam di Madiun bukanlah garis lurus. Ia bernegosiasi dengan adat, kekuasaan, dan kepentingan.
Resistensi nan Sunyi
Sejarah Jawa abad ke-19 sering ditulis lewat perang besar: Diponegoro, Banten, Aceh. Tetapi Madiun tidak punya panggung perang heroik semacam itu. Ia tampak tenang, nyaris anonim dalam arsip kolonial. Namun di balik ketenangan itu, ada resistensi yang berjalan sunyi.
Ong (2018) menyebut resistensi petani Madiun jarang berbentuk frontal. Ia hadir dalam tindakan kecil: menunda setoran pajak, menolak kerja rodi, mencuri hasil panen, atau bermigrasi diam-diam (hlm. 71-72). Dari sudut pandang Belanda, itu hanyalah kelalaian. Namun bagi petani, itu adalah cara menjaga martabat.
James C. Scott (1985) menyebutnya “resistance of the weak”: resistensi sehari-hari yang tidak mencatatkan diri dalam arsip resmi, tetapi justru karena itu sulit ditumpas. Islam memberikan legitimasi moral: sabar dan adil dipahami sebagai etika perlawanan. Pencurian hasil panen untuk keluarga bukan kriminalitas, tetapi survival yang sah secara moral (Ong, 2018, hlm. 75).
Langgar dan masjid membingkai resistensi ini. Doa bukan sekadar ritual, tetapi solidaritas. Kesabaran bukan kelemahan, tetapi bentuk kekuatan. Bahkan priayi kadang masuk dalam resistensi ambigu dengan menoleransi kekurangan setoran pajak.
Dengan demikian, resistensi Madiun adalah perlawanan tanpa perang. Ia hidup dalam cerita mulut ke mulut: tentang petani yang berani menolak rodi, tentang kiai yang mengingatkan keadilan. Cerita ini tidak masuk arsip residen, tetapi bertahan dalam ingatan desa.
Islam sebagai Perekat
Apa yang membuat masyarakat Madiun bertahan? Ong (2018) menjawab: Islam adalah perekat utama. Ia menjaga desa tetap utuh meski pajak dan rodi menekan dari atas (hlm. 81). Masjid menjadi simbol identitas kolektif. Ia berdiri di tengah desa, menjadi ruang doa, musyawarah, hingga pendidikan. Pesantren kecil menjadi simpul jaringan antar-desa, menciptakan kesadaran yang melampaui batas administratif kolonial.
Ritus komunal seperti slametan, meski bercorak sinkretis, dibingkai dalam doa Islam. Idulfitri dan Maulid Nabi menjadi momen solidaritas lintas lapisan sosial. Semua berkumpul, makan bersama, dan merasakan kebersamaan.
Islam, dengan demikian, menjadi cultural system (Geertz, 1973) yang memberi legitimasi moral. Ia menyediakan narasi alternatif terhadap kolonialisme: bahwa penderitaan adalah ujian, solidaritas adalah kewajiban, dan ketidakadilan bukan kehendak Tuhan. Dalam jangka panjang, identitas ini bertahan melampaui kolonialisme. Pola patronase priyayi, solidaritas petani, dan jaringan Kiai tetap hidup hingga abad ke-20. Islam, dengan kata Ong, “menciptakan rasa kebersamaan yang melampaui garis administrasi” (2018, hlm. 83).
Sejarah sering ditulis dari atas: laporan residen, catatan perang, deklarasi politik. Akan tetapi Madiun abad ke-19 mengingatkan bahwa ada sejarah liyan: sejarah yang ditulis dari bawah, dari doa di langgar, dari kerja sunyi di sawah, dari kesabaran yang penuh makna politis.
Islam di Madiun hadir bukan dalam bentuk jihad besar, melainkan dalam etika sehari-hari. Ia menjelaskan penderitaan sebagai ujian, solidaritas sebagai kewajiban, dan kejujuran sebagai fondasi komunitas. Dengan cara itu, Islam menjadi peta makna yang memungkinkan masyarakat menavigasi dunia kolonial yang penuh ketidakpastian. Dentang lonceng gereja Belanda mungkin terdengar lebih keras di udara pagi. Walakin gema azan dari langgar desa, meski lirih, jauh lebih membentuk ritme hidup masyarakat.
Di situlah sejarah ditulis dengan doa, dengan kerja, dengan telaten. Dari sanalah lahir identitas kolektif yang bertahan hingga kiwari.
Resistensi nan Sunyi
Sejarah Jawa abad ke-19 sering ditulis lewat perang besar: Diponegoro, Banten, Aceh. Tetapi Madiun tidak punya panggung perang heroik semacam itu. Ia tampak tenang, nyaris anonim dalam arsip kolonial. Namun di balik ketenangan itu, ada resistensi yang berjalan sunyi.
Ong (2018) menyebut resistensi petani Madiun jarang berbentuk frontal. Ia hadir dalam tindakan kecil: menunda setoran pajak, menolak kerja rodi, mencuri hasil panen, atau bermigrasi diam-diam (hlm. 71-72). Dari sudut pandang Belanda, itu hanyalah kelalaian. Namun bagi petani, itu adalah cara menjaga martabat.
James C. Scott (1985) menyebutnya “resistance of the weak”: resistensi sehari-hari yang tidak mencatatkan diri dalam arsip resmi, tetapi justru karena itu sulit ditumpas. Islam memberikan legitimasi moral: sabar dan adil dipahami sebagai etika perlawanan. Pencurian hasil panen untuk keluarga bukan kriminalitas, tetapi survival yang sah secara moral (Ong, 2018, hlm. 75).
Langgar dan masjid membingkai resistensi ini. Doa bukan sekadar ritual, tetapi solidaritas. Kesabaran bukan kelemahan, tetapi bentuk kekuatan. Bahkan priayi kadang masuk dalam resistensi ambigu dengan menoleransi kekurangan setoran pajak.
Dengan demikian, resistensi Madiun adalah perlawanan tanpa perang. Ia hidup dalam cerita mulut ke mulut: tentang petani yang berani menolak rodi, tentang kiai yang mengingatkan keadilan. Cerita ini tidak masuk arsip residen, tetapi bertahan dalam ingatan desa.
Islam sebagai Perekat
Apa yang membuat masyarakat Madiun bertahan? Ong (2018) menjawab: Islam adalah perekat utama. Ia menjaga desa tetap utuh meski pajak dan rodi menekan dari atas (hlm. 81). Masjid menjadi simbol identitas kolektif. Ia berdiri di tengah desa, menjadi ruang doa, musyawarah, hingga pendidikan. Pesantren kecil menjadi simpul jaringan antar-desa, menciptakan kesadaran yang melampaui batas administratif kolonial.
Ritus komunal seperti slametan, meski bercorak sinkretis, dibingkai dalam doa Islam. Idulfitri dan Maulid Nabi menjadi momen solidaritas lintas lapisan sosial. Semua berkumpul, makan bersama, dan merasakan kebersamaan.
Islam, dengan demikian, menjadi cultural system (Geertz, 1973) yang memberi legitimasi moral. Ia menyediakan narasi alternatif terhadap kolonialisme: bahwa penderitaan adalah ujian, solidaritas adalah kewajiban, dan ketidakadilan bukan kehendak Tuhan. Dalam jangka panjang, identitas ini bertahan melampaui kolonialisme. Pola patronase priyayi, solidaritas petani, dan jaringan Kiai tetap hidup hingga abad ke-20. Islam, dengan kata Ong, “menciptakan rasa kebersamaan yang melampaui garis administrasi” (2018, hlm. 83).
Sejarah sering ditulis dari atas: laporan residen, catatan perang, deklarasi politik. Akan tetapi Madiun abad ke-19 mengingatkan bahwa ada sejarah liyan: sejarah yang ditulis dari bawah, dari doa di langgar, dari kerja sunyi di sawah, dari kesabaran yang penuh makna politis.
Islam di Madiun hadir bukan dalam bentuk jihad besar, melainkan dalam etika sehari-hari. Ia menjelaskan penderitaan sebagai ujian, solidaritas sebagai kewajiban, dan kejujuran sebagai fondasi komunitas. Dengan cara itu, Islam menjadi peta makna yang memungkinkan masyarakat menavigasi dunia kolonial yang penuh ketidakpastian. Dentang lonceng gereja Belanda mungkin terdengar lebih keras di udara pagi. Walakin gema azan dari langgar desa, meski lirih, jauh lebih membentuk ritme hidup masyarakat.
Di situlah sejarah ditulis dengan doa, dengan kerja, dengan telaten. Dari sanalah lahir identitas kolektif yang bertahan hingga kiwari.