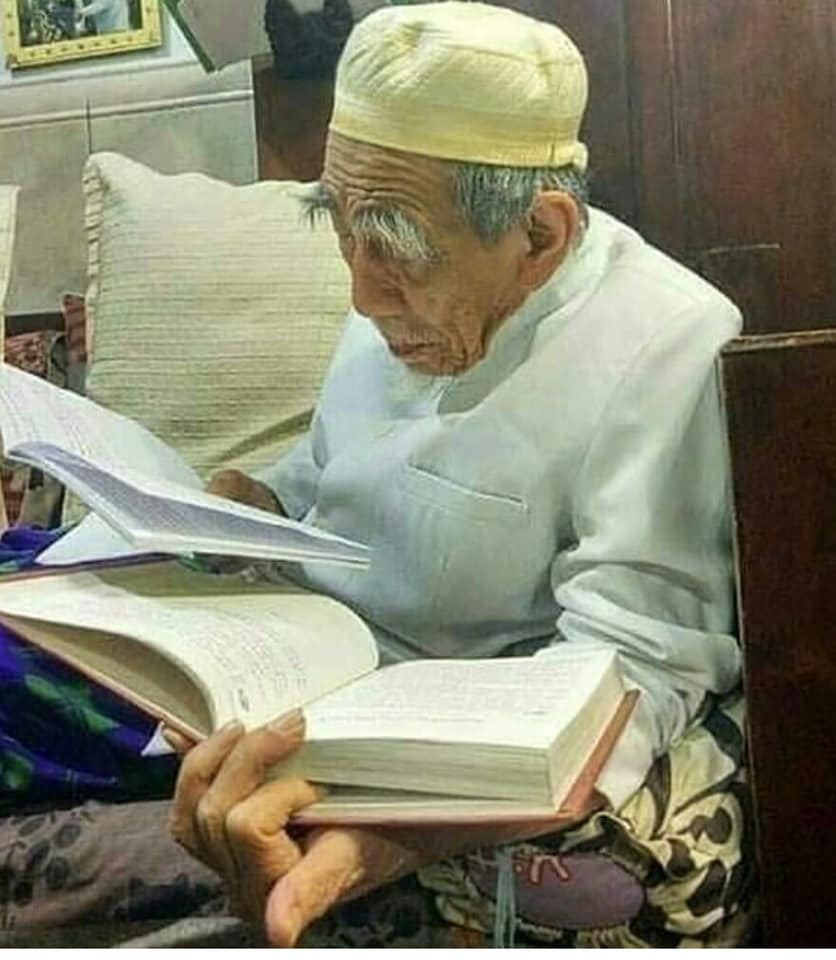Edward Said berdiri di persimpangan antara dunia akademik dan perlawanan di antara nama-nama besar abad ke-20. Ia bukan hanya seorang profesor di Columbia University, tetapi juga wajah bagi bangsa yang tak memiliki negara. Ia lahir di Jerusalem pada 1935, di sebuah wilayah yang kemudian menjadi medan sengketa tanpa akhir. Ia tumbuh di Kairo, menimba ilmu di Princeton dan Harvard, dan hidup di Amerika Serikat sebagai warga dunia yang terus dihantui kenangan tentang tanah yang hilang. Dalam diri Said, eksil bukan sekadar nasib pribadi, tetapi luka kolektif bangsa Palestina. Timothy Brennan dalam bukunya Places of Mind: A Life of Edward Said (Bloomsbury Publishing, 2021) mendedah bahwa Said “menulis dari jantung imperium, tetapi suaranya selalu bergema untuk mereka yang dibungkam.”
Said tidak pernah melihat dirinya hanya sebagai pengamat. Ia hidup di antara dua dunia yang saling mencurigai: Timur dan Barat, Islam dan sekularisme, Palestina dan Amerika. Ia tahu bahwa menjadi intelektual berarti menanggung beban moral untuk berbicara melawan kekuasaan. Itulah sebabnya tulisannya terasa seperti perlawanan yang tenang, bukan dengan senjata, tetapi dengan kata. Dari awal kariernya, ia meyakini bahwa pengetahuan tidak netral. Ia dapat menjadi alat pembebasan, tetapi juga instrumen penindasan. Dalam buku Orientalism (1978), ia menunjukkan bagaimana Barat membangun citra “Timur” sebagai sesuatu yang eksotis, irasional, dan inferior, semata agar bisa membenarkan kolonialisme. Kritik ini tidak hanya mengguncang dunia akademik, tetapi juga membuka ruang baru bagi bangsa-bangsa yang lama didiamkan sejarah.
Namun bagi Said, kritik terhadap wacana kolonial hanyalah permulaan. Di balik teori dan filsafatnya, ada dorongan yang jauh lebih pribadi: kerinduan terhadap tanah kelahirannya. Dalam esai terkenalnya Permission to Narrate, ia meneroka bahwa kekuasaan kolonial bekerja bukan hanya melalui militer atau ekonomi, tetapi juga melalui narasi. Bangsa yang tidak diizinkan bercerita akan lenyap dari peta sejarah. Israel memiliki Exodus, kisah heroik tentang pengembaraan dan penebusan. Palestina hanya memiliki sunyi. Said menulis bahwa “tidak ada bangsa yang bisa dihormati jika ia tidak dapat menceritakan kisahnya sendiri.” (Brennan, 2021, hlm. 212).
Dari kesadaran inilah lahir gagasan Palestinianism. Ia bukan sekadar nasionalisme baru, tapi cara untuk mengembalikan suara yang dirampas. Dalam pandangan Said, orang Palestina bukan korban pasif yang tinggal di tenda-tenda pengungsi. Mereka adalah bangsa yang hidup di antara banyak bangsa, yang menjadikan perpindahan dan pertemuan sebagai bentuk kekuatan. Palestinianism bukan politik identitas yang ketang, melainkan simbol universal dari perlawanan terhadap penindasan (Brennan, 2021, hlm. 214).
Konsep ini membuat Said berbeda dari banyak intelektual lain pada masanya. Ia menolak melihat Palestina hanya sebagai konflik regional, tetapi sebagai cermin dunia modern. Di sana, kata Said, semua kontradiksi abad ke-20 bertemu: kolonialisme, nasionalisme, agama, dan imperialisme. Bagi banyak aktivis, Palestina adalah ukuran sejauh mana seseorang berani bersikap melawan ketidakadilan. “Mengkritik Israel,” tulis Brennan (2021, hlm. 215), “sering berarti mengorbankan reputasi atau bahkan kehilangan pekerjaan.” Tetapi bagi Said, diam jauh lebih berbahaya.
Dalam perjalanan hidupnya, Edward Said tidak pernah memisahkan pemikiran dan politik. Ia bukan akademisi menara gading. Ia menulis dengan darah sejarah bangsanya. Ia menjadi juru bicara tak resmi bagi Palestina di New York. Ia mengajarkan teori sastra di ruang kuliah, tetapi di podium publik ia membela hak rakyatnya untuk hidup bebas. Hubungannya dengan Yasser Arafat memperlihatkan dilema yang selalu dihadapi oleh intelektual yang berjuang dari luar kekuasaan. Ia menghormati Arafat sebagai simbol perjuangan, tetapi juga mengkritiknya karena terlalu mudah berkompromi.
Said sering berbicara dengan Arafat dalam bahasa Arab, dengan aksen Levantine nan lembut. Brennan (2021, hlm. 148) mencatat bagaimana mereka berdebat hangat tentang strategi politik dan citra publik Palestina. Arafat, dengan keffiyeh dan seragam militernya, dianggap Said terlalu mudah menjadi karikatur bagi media Barat. Ia menulis kepada sahabatnya Alexander Cockburn agar menasihati Arafat lewat kolomnya di Interview Magazine. Namun, meski sering kecewa, Said tidak pernah sepenuhnya meninggalkan Arafat. Ia tahu bahwa tanpa figur itu, semangat kolektif Palestina bisa tercerai-berai.
Segalanya berubah ketika perjanjian Oslo ditandatangani titimangsa 1993. Perjanjian itu, yang dirancang secara rahasia antara pejabat PLO dan Israel, disebut Brennan sebagai “perdamaian tanpa keadilan” (2021, hlm. 319). Said menolak menandatangani euforia diplomatik yang melanda dunia. Ia melihat bahwa Oslo bukan solusi, melainkan jebakan. Palestina memang diakui, tetapi hanya sebagai entitas administratif yang tunduk pada kontrol Israel. Dalam pandangan Said, Oslo mengubah revolusi menjadi birokrasi. Ia mendedah bahwa “tidak ada kemerdekaan sejati jika keadilan diserahkan pada kompromi politik.”
Pandangan ini membuat Said kehilangan banyak teman. Sebagian menuduhnya idealis, bahkan sinis. Walakin waktu membuktikan bahwa kecemasannya benar. Dua dekade setelah Oslo, Palestina masih terpecah, wilayahnya terkurung, dan rakyatnya hidup di bawah pendudukan yang semakin sistematis. Said tidak melihat dirinya sebagai nabi. Ia hanya menolak untuk menipu diri sendiri. Ia tahu bahwa perdamaian yang lahir dari ketidaksetaraan tidak akan pernah bertahan lama.
Di balik sikap politiknya yang keras, ada sisi personal nan lembut. Said adalah pencinta musik klasik. Ia menulis dengan ketelitian seorang pianis yang menghafal partitur. Musik baginya adalah bentuk kebebasan yang paling jujur. Bersama Daniel Barenboim, seorang konduktor Yahudi kelahiran Argentina, ia mendirikan West-Eastern Divan Orchestra. Orkestra ini mempertemukan musisi muda Arab dan Israel dalam satu panggung. Mereka memainkan Beethoven, Wagner, dan Mozart tanpa batas kebangsaan. Bagi Said, proyek itu bukan sekadar eksperimen seni. Ia adalah pernyataan moral: bahwa harmoni hanya mungkin jika semua suara didengar.
Said sering menulis bahwa musik mengajarkan manusia untuk mendengar tanpa menguasai. Dalam setiap simfoni, ada kesunyian yang memberi ruang bagi yang lain. Ia percaya bahwa di sanalah inti kemanusiaan berada. Brennan (2021) menyebutnya “intelektual yang menemukan etika di dalam estetika.” Di tengah dunia yang dipenuhi slogan politik, Said memilih berbicara lewat nada. Ia percaya bahwa keindahan dapat menjadi bentuk perlawanan yang paling nyenyat.
Namun, kesunyian itu bukan pelarian. Said tahu bahwa menjadi intelektual berarti selalu berada di tengah badai. Ia sering diserang oleh media pro-Israel, diawasi oleh FBI, dan disalahpahami oleh sebagian kalangan Arab sendiri. Akan tetapi ia tidak pernah berhenti menulis. Ia menulis karena baginya, menulis adalah bentuk eksistensi. “Menulis adalah cara untuk melawan penghapusan,” katanya dalam satu wawancara. “Jika kami tidak menulis, kami akan benar-benar hilang.”
Kehidupan Said adalah perjalanan panjang antara bahasa dan kehilangan. Sejak kecil, ia terbelah oleh tiga bahasa: Arab, Inggris, dan Prancis. Ayahnya berbicara dalam bahasa Inggris dengan logat Amerika, ibunya dalam Prancis yang halus, dan di sekolah ia belajar Alkitab dalam bahasa Arab klasik. Campuran ini menjadikannya kosmopolitan, tetapi juga terasing. Ia sering berkata bahwa ia tidak pernah merasa “di rumah” di mana pun. Namun justru dari keterasingan itu lahir kepekaan yang luar biasa. Ia tahu bahwa dunia tidak pernah sesederhana dikotomi Timur dan Barat.
Dalam tulisan-tulisan terakhirnya, Said semakin banyak berwicara tentang penyakitnya, leukemia, yang dideritanya selama bertahun-tahun. Ia menulis dengan kesadaran bahwa waktu tidak lagi berpihak. Namun, seperti dalam musik yang ia cintai, ia tetap menjaga tempo. Ia menolak rasa iba. Ia menulis tentang kematian seperti ia menulis tentang kolonialisme: dengan kejernihan yang nyaris menyakitkan.
Tatkala ia wafat tanggal 25 September 2003, dunia kehilangan suara yang paling berani dalam membela kemanusiaan. Namun, warisan intelektualnya tidak mati. Buku-bukunya tetap dibaca di universitas-universitas di seluruh dunia. Di Gaza dan Ramallah, namanya disebut oleh anak-anak muda yang belajar menulis sebagai bentuk perlawanan. Di ruang-ruang diskusi, ide-idenya tentang “narasi” dan “representasi” menjadi panduan bagi mereka yang berjuang melawan penindasan dalam berbagai bentuk.
Dalam dunia yang kiwari kembali dipenuhi perang, diskriminasi, dan kebohongan politik, Edward Said terasa semakin relevan. Ia mengingatkan bahwa pertempuran paling penting bukanlah di medan perang, tetapi di wilayah makna. Siapa yang berhak mendefinisikan sejarah? Siapa yang berhak berbicara tentang siapa? Pertanyaan-pertanyaan itu masih menggantung, sama seperti luka Palestina yang tak kunjung sembuh.
Said pernah menulis bahwa “Palestina adalah ujian moral bagi dunia.” Jika dunia patah pucuk mendengarkan jeritan rakyat Palestina, maka dunia telah gagal memahami arti keadilan itu sendiri. Di sinilah makna paling dalam dari warisan intelektualnya: bahwa solidaritas bukan belas kasihan, melainkan keberanian untuk mengakui kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu tidak populer.
Hari ini, bayangan Said terasa hadir di setiap gambar reruntuhan Gaza yang beredar di layar. Ia seolah berwicara kepada dunia yang masih tuli terhadap penderitaan bangsanya. Ia mungkin akan berkata bahwa kekerasan bukan takdir, bahwa perdamaian sejati hanya lahir dari kesetaraan, dan bahwa setiap bangsa berhak menulis kisahnya sendiri.
Edward Said telah pergi, tetapi kata-katanya masih hidup, berkelana di antara puing-puing sejarah laksana debu yang menolak tenggelam. Ia mengajarkan bahwa menulis bisa menjadi bentuk doa, dan berpikir bisa menjadi bentuk cinta. Di tengah dunia yang retak oleh kebencian, suaranya tetap menjadi pengingat bahwa kemanusiaan bukan sekadar konsep, melainkan perjuangan yang harus diperjuangkan setiap hari.
Bagi Palestina, ia bukan hanya seorang intelektual, tetapi juga rumah. Sebuah rumah dari kata-kata, dari ingatan, dan dari asa yang belum mati.