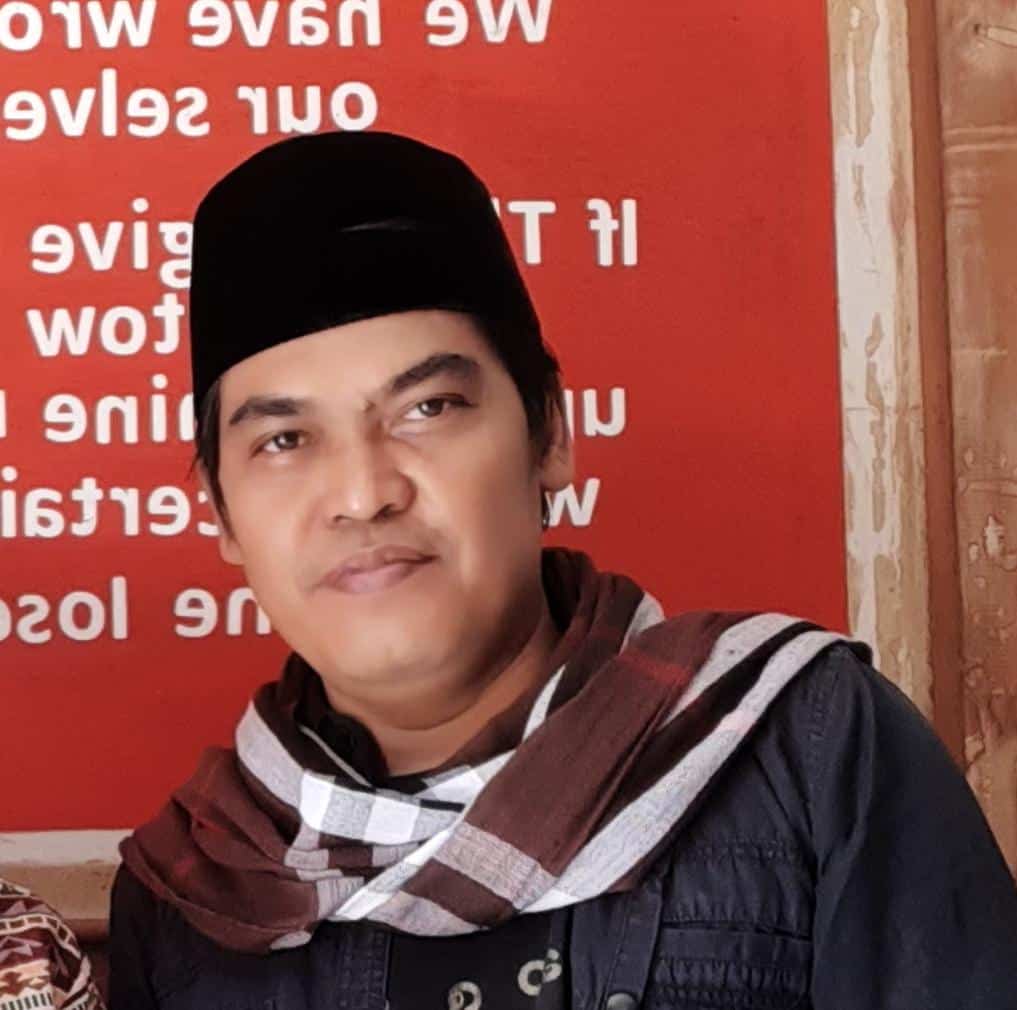Asal-usul Pesantren: Anak Sungai dari Tradisi Keraton
Dari akar budaya keraton, pesantren menumbuhkan pohon ilmu yang rindang, tempat dimana santri belajar menjadi manusia rendah hati, berpikir kritis, dan berkhidmah.

Mereka hanya melihat yang kasat mata, tak mampu menelisik lebih dalam lantaran terhalang ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu muncul karena cara pandang yang etik -- pandangan luaran yang memaksakan sudutnya sendiri terhadap sesuatu yang berdiri di luar jangkauan dan frekuensinya. Jika sejak awal sudah salah angle, salah frekuensi, ditambah sikap apriori, takabur, jumawah, pokoknya “tak sukak”, maka ujung-ujungnya pasti menghinakan, membusukkan, menyesatkan. Begitulah yang sering terjadi ketika orang menilai pesantren tanpa memahami konteks kulturalnya.
Mau diakui atau tidak, Islam di Indonesia pertama-tama diperkuat oleh pesantren. Sebelum pesantren lahir, masyarakat Nusantara telah mengenal padepokan, asrama, dukuh, paguron, baru kemudian pesantren, sebelum disusul sistem sekolahan seperti sekarang. Artinya, pesantren bukan sekadar lembaga keagamaan, tetapi hasil evolusi panjang dari tradisi pendidikan dan spiritualitas lokal yang telah berakar jauh sebelum Islam datang.
Menurut almaghfurlah Kiai Agus Sunyoto, kesalahan besar para sarjana Belanda adalah menafsirkan kiai dan pesantren dengan kacamata Barat. Mereka menganggap kiai sebagai “agamawan” seperti pastur atau pendeta dalam tradisi Kristen. Padahal di Nusantara, kiai sejak awal bukan golongan agamawan, melainkan keluarga keraton, bangsawan, bahkan keturunan raja. Sunan Ampel dan Sunan Giri, misalnya, adalah keturunan raja. Kiai Nur Iman, pendiri Pesantren Mlangi di Yogyakarta, adalah kakak tertua Sultan Hamengkubuwono I. Begitu juga Pesantren Babakan Ciwaringin. Bahkan Pesantren Krapyak Jogja, ada relasi dengan keratonnya.
Tak sedikit pesantren di Jawa berdiri dari tangan kerabat keraton dan patriot pengikut Pangeran Diponegoro yang menyebar saat pengejaran Belanda. Ponpes Langitan Tuban, misalnya, didirikan oleh Kiai Muhammad Nur, pengikut Diponegoro dan keturunan Pangeran Sambo, putra Pangeran Benowo, cucu Jaka Tingkir, Sultan Pajang. Pendiri Tebuireng Jombang, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari, juga merupakan keturunan Pangeran Benowo hingga Sunan Giri dan Brawijaya IV. Maka wajar jika pesantren membawa warisan budaya keraton dalam bentuk tata krama, penghormatan, dan hirarki sosial.
Namun warisan itu tidak diterima mentah. Pesantren mentransformasinya secara mendasar. Jika di keraton relasi raja dan kawula berdiri di atas dasar kekuasaan dan ketertundukan, maka di pesantren hubungan kiai dan santri dibangun atas dasar rahmah, cinta kasih, ilmu, dan spiritualitas. Relasi itu bukan lagi kekuasaan, tetapi bimbingan tarbiyah wa ta’lim, mentoring ruhani. Santri tunduk kepada kiai bukan karena takut, tapi karena yakin keberkahan ilmu lahir dari adab dan kerendahan hati, di mana relasi keduanya terhubung dengan hidayah dan terbukanya pintu-pintu pengetahuan yang tak terbatas pada aspek kognitif belaka.
Ketika seorang santri diantar mondok oleh orang tuanya, tradisi pertama yang dilakukan adalah sowan kepada kiai atau nyai pengasuh. Di situlah sinyal synch dimulai -- sebuah proses penyesuaian frekuensi. Bahwa sang anak “dititipkan” di pesantren bukan sekadar untuk ditaklim, tapi juga ditarbiyah. Bukan hanya diisi pengetahuan kognitif, tetapi juga ditempa laku dan pengalamannya. Frekuensi ini menghubungkan kiai sebagai transmisi pengetahuan yang tak semata kognitif, tetapi juga pengalaman, rasa (dzauq), dan spiritualitas. Itulah kenapa setiap santri pondok pesantren sudah pasti mengenal dan bahkan hafal isi nazam Alala dan akan memulai "debut study"nya dengan bekal Ta’limul Muta’allim, kitab yang menegaskan bahwa adab lebih tinggi dari ilmu. Di sini, kiai bukan hanya sebagai pengajar (mualim) tetapi murobbi ruh, pembimbing, pendidik ruhani. Dan karena itu pulalah barokah menjadi “isu sentral” di pesantren, yaitu sang kiai disebut sebagai pengasuh, bukan kepala lembaga apalagi direktur dalam pengertian teknis.
Tradisi cium tangan, menunduk sopan, bersimpuh, bahkan ngesot ketika sowan (namun harus diingat, tiap pesantren memiliki tradisi sendiri), bukanlah bentuk keberbudakan seperti tuduhan sebagian orang yang gagal memahami subkultur pesantren. Ia adalah ekspresi tawadhu’, kerendahan hati yang membuka dada terhadap limpahan cahaya ilmu. Sebab dalam pandangan santri, al-‘ilm nūrun, ilmu adalah cahaya. Dan cahaya hanya memantul pada hati yang bersih dan penuh hormat.
Begitu pula dengan budaya ro’an (asal dari tabarrukan atau ngalap berkah) yang belakangan dituduh sebagai eksploitasi tenaga anak. Padahal, itu adalah ekspresi kebersamaan dalam menjaga ruang ngelmu secara kolektif-partisipatif, demi ridha guru dan Allah Sang Cahaya. Melalui ro’an, santri belajar bahwa keberkahan ilmu tak hanya lahir dari membaca kitab, tetapi juga dari kerja ikhlas yang menjaga kehidupan pesantren, dari peluh yang disertai niat pengabdian. Di situlah letak makna mendalam “kerja sebagai ibadah” yang hidup nyata dalam laku santri.
Menariknya, meski berakar dari tradisi keraton yang feodal, pesantren justru tumbuh menjadi ruang paling “liberal” dalam dunia Islam Nusantara. Di sini, perbedaan pandangan bukan dihindari, justru dirayakan. Forum bahtsul masail menjadi bukti keterbukaan itu. Di ruang dialektika ini santri beradu argumen dengan dalil, mencari kebenaran bersama, tanpa merasa paling benar. Tidak ada pendapat yang harus diikuti secara mutlak. Setiap orang bebas berpikir dan menyampaikan pandangannya selama berbasis literatur dan tetap mengedepankan adab.
Kiai Agus Sunyoto juga mencatat, ketika kekuatan keraton melemah di masa penjajahan, pesantren justru mengambil alih peran sebagai benteng terakhir perlawanan. Tercatat 112 pemberontakan dipimpin oleh guru tarekat dan kiai pesantren yang tak lain adalah pewaris sah tradisi keraton yang direndahkan oleh sistem kolonial. Saat Belanda membagi masyarakat menjadi kelas kulit putih, Timur Asing, dan pribumi paling bawah, pesantren berdiri tegak sebagai ruang perlawanan moral dan spiritual untuk menjaga martabat bangsa.
Maka dengan demikian, benar kiranya jika pesantren disebut anak sungai dari tradisi keraton. Sebab ia mengalir dari sumber yang sama, meskipun menuju muara yang berbeda. Jika keraton adalah simbol kekuasaan duniawi, pesantren menjelma menjadi simbol kebebasan spiritual dan intelektual. Ia mengubah warisan feodal menjadi etika keilmuan, mengalirkan nilai-nilai adab menjadi energi pembebasan, dan menanamkan kesetaraan dalam pencarian ilmu dan kebenaran.
Pesantren bukan lembaga yang menundukkan, melainkan yang membebaskan. Bukan tempat mengkultuskan, melainkan tempat menumbuhkan. Dari akar budaya keraton, pesantren menumbuhkan pohon ilmu yang rindang, tempat dimana santri belajar menjadi manusia rendah hati, berpikir kritis, dan berkhidmah. Pesantren memang anak sungai keraton, tapi dari mata air feodal itu, ia mengalir menjadi samudra kebebasan ilmu dan spiritualitas.